Ditapis dengan
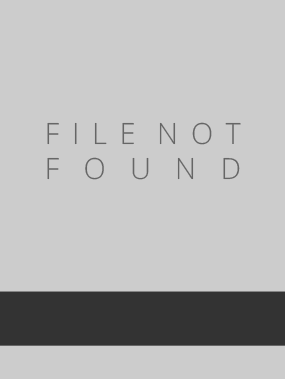
Panduan praktis USG dan CTG pada kehamilan dan persalinan
Buku ini untuk menjelaskan seluruh bidang diagnostik prenatal dan tatalaksananya. Materi yang dibahas adalah USG dan CTG. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) obstetri pada saat ini pemeriksaannya sudah mirip dengan pemeriksaan fisik diagnostik memakai stetoskop. Materi bahasan pada pemeriksaan (USG) obstetri pada kelainan medik dalam kehamilan, persalinan dan pascapersalinan dibuat secara praktis dan diharapkan dapat diterapkan di Indonesia. Materi bahasan mencakup: 1. Persiapan pemeriksaan USG. Indikasi pemeriksaan USG obstetri. Tara cara pemeriksaan USG OBGIN. Panduan POGI dalam pemeriksaan USG obstetri. Pemeriksaan USG pada kelainan medik dalam kehamilan. Aspek etika-medikolegal dalam pemeriksaan USG. Dokumentasi dan pembuatan laporan USG. 2. CGT atau kardiotokografi satu-satunya metode penilaian insufisiensi uteroplasenta terbaik saat kehamilan dan persalinan, terutama pada resiko tinggi. CGT atau kardiotokografi merupakan seperangkat peralatan elektronik yang dapat dipergunakan untuk memantau kesejahteraan janin. Alat ini terdiri dari dua komponen utama yaitu kardiografi untuk memantau denyut jantung janin (DJJ) dan tokografi untuk memantau kontraksi uterus dan gerak janin. Kata kunci: USG, CTG, kehamilan, persalinan

Kamus Saku Kedokteran Dorland

Pengaruh total iskemik time terhadap penurunan kadar kreatinin dan produksi urin resipien pasca transplantasi ginjal (studi observasional di RSUP Dr. Kariadi Semarang 2014-2018)
Pendahuluan: Transplantasi ginjal diakui sebagai kemajuan besar dalam pengobatan modern yang memberikan tahun-tahun kehidupan berkualitas tinggi kepada pasien dengan gagal ginjal yang ireversibel (penyakit ginjal stadium akhir, ESRD) di seluruh dunia. Di Semarang, transplantasi ginjal pertama adalah Rumah Sakit Telogorejo pada tahun 1985. Di Rumah Sakit Dr. Kariadi, transplantasi ginjal telah dilakukan 28 kali sejak Januari 2014 hingga September 2018. Waktu iskemik ginjal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil transplantasi ginjal. Iskemik cangkok yang berkepanjangan dapat dikaitkan dengan efek transplantasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh total waktu iskemik dengan hasil transplantasi ginjal di Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang. Metode: Ini adalah observasional, studi cross sectional. Data dikumpulkan dari rekam medis. Subjek penelitian ini adalah semua pasien yang menjalani transplantasi ginjal yang tercatat dalam rekam medis dari Januari 2014 hingga Desember 2018 dan tingkat produksi kreatinin dan urin sebelum dan sesudah transplantasi didokumentasikan. Ada 28 pasien yang termasuk dalam kriteria inklusi. Hasil penelitian akan ditabulasi dan perhitungan statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS 23.0. Hubungan dinyatakan bermakna jika p = 0,05 diperoleh. Hasil: Dari analisis penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Pearson dan uji hipotesis Wilcoxon dan ditemukan bahwa ada hubungan antara waktu iskemik dan penurunan kreatinin ginjal dari r = -0,4489 dengan nilai p = 0,008 . Dari analisis penelitian yang telah dilakukan, terdapat hubungan antara waktu iskemik dan produksi urin pasca transplantasi dengan nilai r = -0,562 dan nilai p = 0,002. Kesimpulan: Dari hasil penelitian ini terdapat korelasi yang kuat antara panjang total waktu iskemik dengan penurunan produksi kreatinin dan urin yang berarti bahwa semakin lama waktu iskemik semakin rendah penurunan kadar kreatinin dan semakin sedikit produksi urin. Kata kunci: Total Waktu Iskemik, Tingkat Kreatinin, Produksi Urin, Transplantasi Ginjal

Gambaran karakteristik pasien hidrocephalus dengan ekspulsi ventriculoperitoneal shunt di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Juni 2014-Juni 2016
Latar belakang : Hidrosefalus sebagian besar diterapi dengan pemasangan VP-shunt. Salah satu komplikasi pemasangan VP-shunt adalah ekspulsi VP-Shunt. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran deskriptif pasien hidrosefalus dengan ekspulsi VP Shunt di RSUP Dr. Kariadi pada periode Juni 2014 – Juni 2016. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian "deskriptif retrospektif", pada pasien hidrosefalus yang mengalami ekspulsi VP Shunt yang dirawat pada periode Juni 2014 – Juni 2016 . Hasil : Terdapat 13 pasien mengalami kasus ekspulsi VP shunt. Diantaranya 6 pasien berusia kurang dari 6 bulan, 3 pasien usia 6-12 bulan , dan 4 pasien berusia lebih dari 12 bulan. Sebanyak 10 pasien (77 %) mengalami gizi kurang, 2 pasien (15%) mengalami gizi buruk , dan 1 pasien (8%) memiliki status gizi yang baik. Distribusi lokasi terjadinya ekspulsi shunting yaitu sebanyak 7 pasien berada di abdomen, 5 pasien terjadi di kepala dan 1 pasien terjadi di anal. Kesimpulan : penderita hidrosefalus yang mengalami ekspulsi VP Shunt di RSUP Dr. Kariadi Semarang pada Juni 2014 – Juni 2016 sebanyak 13 kasus. Dengan rentang usia terbanyak 0-6 bulan. Dari seluruh pasien yang diteliti, rata-rata mengalami gizi buruk .Lokasi yang sering terjadi ekspulsi yaitu di abdomen. Kata kunci : Hidrosefalus, VP-Shunt, eksplusi.

Pengaruh pemberian eicosapentaenoic acid (EPA) terhadap penurunan kadar calsium dalam urine dan kadar calsium dalam darah
Latar Belakang : Konsumsi asam eicosapentaenoic (EPA) terkait dengan pengurangan faktor patogen dalam urin. EPA merupakan inhibitor metabolisme asam arakidonat mengakibatkan sintesis penurunan prostaglandin E2, suatu zat yang dikenal menyebabkan ekskresi kalsium urin. Untuk mengatasi batu berulang hypercalciuric dengan memberikan selama 8 minggu minyak ikan dan didapatkan ekskresi oksalat dan kalsium berkurang secara signifikan. Dinilai dalam tiga tahap; fase-I sebelum pemberian EPA (berarti 47,8 bulan), fase-II suplementasi EPA (1800 mg / d; berarti 36,4 bulan) dan fase-III setelah menghentikan EPA (berarti 50,6 bulan). Mereka mengamati penurunan signifikan secara statistik selama fase suplemen dari sebelumnya atau setelah (0,22, 0,07 dan 0,17 kali / tahun, masing-masing; RR 3,29 sebelum dan RR 2,51 setelah EPA)5,8. Metode : Penelitian ini adalah penelitian true experimental dengan rancangan Randomized control trial. Terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kelompok kontrol, yaitu Pegawai dan dokter Internship yang mendapatkan terapi eicosapentanoic acid 1800 mg per hari selama 2 minggu.Kelompok perlakuan, yaitu kelompok pasien- pasien non batu / non urologi yang dirawat di RSUD Jampang Kulon, Sukabumi yang mendapatkan terapi eicosapentanoic acid 1800 mg per hari selama 2 minggu.Data Data hasil penelitian berupa pemeriksaan kadar kalsium dalam serum darah dan urine yang setelah dan sebelum pemberian EPA kemudian dibandingkan dengan kadar kalsium dalam darah dan urin pasien dengan pemberian placebo , dilakukan uij normalitas Saphiro-wilk. Hasil uji normalitas menampilkan distribusi data normal (P>0.05) sehingga memenuhi syarat untuk uji parametrik Independent T-test (T-test tidak berpasangan) dan untuk data yang tidak normal dilakukan uji tidak berpasangan dilakukan uji Mann Whitney. Hasil : Pada Uji ini didapatkan perbedaan yang bermakna kadar kalsium dalam urine pada kelompok kasus pre (171,92 ± 8,05) dan pada kelompok kasus post (166,85 ± 7,35) dengan P < 0,05 sedangkan kelompok kontrol pre (171,92 ± 8,05) dan pada kelompok kontrol post (171,84 ± 7,96) tidak terdapat perbedaan bermakna dengan P > 0,05. Pada uji normalitas selisih kadar kalsium urine kasus dan kontrol menggunakan Shapiro-Wilk dengan hasil normal P > 0,05.Pada Uji ini didapatkan perbedaan yang bermakna kadar kalsium dalam serum pada kelompok kasus pre (9,93 ± 0,70) dan pada kelompok kasus post (9,53 ± 0,70) dengan P < 0,05 sedangkan kelompok kontrol pre (9,93 ± 0,70) dan pada kelompok kontrol post (9,91 ± 0,63) tidak terdapat perbedaan bermakna dengan P > 0,05. Pada uji normalitas selisih kadar kalsium serum kasus menggunakan Shapiro-Wilk dengan hasil normal P > 0,05 sedangkan selisih kadar kalsium serum kontrol tidak normal P

Perbandingan efektivitas kombinasi gellfoam dengan povidone iodine dibanding mikonazol krim terhadap terapi otomikosis
Latar Belakang : Otomikosis sering ditemukan pada daerah tropis dan subtropis di dunia. Secara geografis Indonesia termasuk negara tropis. Prevalensi otomikosis negara berkembang cukup tinggi. Di India dilaporkan otomikosis sebesar 22.73%. Daerah tropis dan subtropics, pembersihan dan pengeringan menyeluruh pilihan terbaik. Tujuan : Membuktikan pemberian kombinasi povidone iodine dengan gelfoam lebih efektif dibandingkan mikonazol krim. Metode : Penelitian menggunakan pasien sebagai subjek penelitian. Penelitian bersifat intervensi dengan pre dan post design. Kombinasi gellfoam dengan povidone iodine dan terapi mikonazol krim merupakan variable bebas, perubahan klinis rasa gatal, penuh, dan nyeri diukur dengan VAS, pengecatan jamur merupakan variable tergantung. Data berskala nominal di uji Mcnemar data berskala numerik dengan uji t berpasangan apabila sebaran data normal dan uji Wilcoxon dan friedman apabila sebaran data tidak normal. Hasil : 48 Subjek otomikosis di evaluasi keluhan klinik, pengecatan jamur. Kedua kelompok rerata keluhan otalgia semakin berkurang nilai p antara keluhan sebelum dan sesudah terapi adalah p 0.05). Hasil pemeriksaan KOH sebelum dan setelah terapi menunjukkan efektivitas secara statistic sama. Kesimpulan : Efektifitas menngurangi keluhan klinis otomikosis dan pengecatan jamur kombinasi povidone iodine dengan gellfoam lebih efektif untuk mengurangi keluhan otalgia dan gatal. Kata kunci : Otomikosis, efektifitas, kombinasi povidone iodine dan gellfoam, mikonazol krim.

Faktor risiko infeksi citomegalovirus pada bayi dan anak yang dicurigai kurang pendengaran
Latar belakang : Infeksi Citomegalovirus (CMV) merupakan infeksi kongenital tersering pada bayi dan anak, 1 – 6% bayi lahir hidup. Infeksi CMV menimbulkan kecacatan permanen, salah satunya kurang pendengaran. Tujuan: Mengetahui faktor risiko infeksi CMV pada anak yang dicurigai kurang pendengaran. Metode: Penelitian belah lintang di Clinic Diagnostic RSUP Dr Kariadi Semarang periode Januari-Maret 2019. Sampel ditentukan sebanyak 97 anak dengan kecurigaan kurang pendengaran, yang memenuhi kriteria inklusi, ekslusi. Diagnosis dan derajat kurang pendengaran berdasar pemeriksaan Brainstem Evoked Response Audiometry, Otoacustic Emission dan timpanometri. Infeksi CMV ditentukan dengan pemeriksaan laboratorium. Analisis data menggunakan uji Chi- square. Hasil: Didapatkan 56 (57,7%) anak kurang dengar, kurang pendengaran derajat berat-sangat berat didapatkan pada 48 (85,71%) anak. Infeksi CMV didapatkan pada 59 (60,8%) anak dengan kadar IgG CMV diatas 25UI/ml sebanyak 43(72,88%) anak. Infeksi CMV merupakan faktor resiko kurang pendengaran (p

Faktor risiko yang mempengaruhi kejadian obstructive sleep apnea pada penderita penyakit jantung koroner
Latar belakang: Faktor risiko yang menyebabkan kejadian obstructive sleep apnea (OSA) pada penderita Penyakit Jantung Koroner (PJK) dapat memperberat gejala kardiovaskularnya dan berakhir dengan perburukan. Prevalensi OSA pada penderita PJK sulit diketahui, 80% penderita PJK tidak menjalani screening awal OSA. Tujuan: Mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian OSA pada penderita PJK. Metode: Penelitian observasional analitik dengan design belah lintang. Sampel adalah penderita PJK yang di rawat inap di Unit pelayanan Jantung RSUP Dr. Kariadi Semarang periode Mei-Agustus 2018. Diagnosis OSA berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik THT, kuesioner Epworth Sleepiness Scale (ESS) dan pemeriksaan Nocturnal Pulse Oximetry. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square, fisher’s exact test, dan regresi logistik. Hasil: Sebanyak 90 pasien PJK, 56 (62,2%) terdiagnosis OSA. Obesitas, lingkar leher besar, hipertrofi tonsila palatina dan makroglosia merupakan faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian OSA, sedangkan hipertrofi konka (P=0,765) dan septum deviasi (p=0,133) tidak berpengaruh terhadap kejadian OSA. Makroglosia merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kejadian OSA (p= 0,001, RP = 82,44,CI 95% =19,154-354,857). Kesimpulan: Obesitas, lingkar leher besar, hipertrofi tonsila palatina dan makroglosia berpengaruh terhadap kejadian OSA pada penderita PJK. Kata kunci: Obstructive Sleep Apnea, penyakit jantung koroner, Nocturnal Pulse Oximetry, Oxygen Desaturation Index

Hubungan gambaran histopatologi & derajat konka hipertrofi dengan sumbatan hidung pada rinosinusitis kronik
Pendahuluan : Konka hipertrofi adalah pembesaran konka karena ukuran selnya yang meningkat, hal ini disebabkan karena hiperplasia dan hipertrofi lapisan mukosa dan tulang konka. Dua puluh persen populasi dengan hidung tersumbat disebabkan konka hipertrofi. Konka hipertrofi dibagi 4 derajat, yaitu derajat 1, derajat 2, derajat 3 dan derajat 4. Gejala hidung tersumbat sering ditemui, dan dapat dinilai dengan pemeriksaan subyektif dan obyektif. Pemeriksaan subyektif dapat menggunakan kuesioner salah-satunya adalah Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE). Tujuan : Mengetahui hubungan gambaran histopatologi dan derajat konka hipertrofi dengan sumbatan hidung pada pasien rinosinusitis kronik. Material dan Metode : Desain penelitian korelatif dengan metode belah pada 33 pasien rinosinusitis kronik (RSK) dengan konka hipertrofi yang menjalani operasi Bedah Sinus Endoskopik Fungsional (BSEF) dan konkotomi. Pasien dilakukan anamnesis dengan kuesioner NOSE, endoskopi, dan histopatologi jaringan konka hipertrofi. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji korelasi Spearman. Hasil Penelitian : Karakteristik subyek penelitian sebanyak 33 orang, laki-laki sebanyak 13 (39,3%) orang dan perempuan sebanyak 20 (60,7%) orang. Sumbatan hidung terbanyak adalah derajat ringan dan berat yaitu masing-masing sebanyak 10 (30,3%) orang. Konka hipertrofi terbanyak adalah derajat 3 yaitu sebanyak 18 (54,54%) subyek. Gambaran histopatologi yang terbanyak adalah hiperplasia sel goblet derajat 3 sebanyak 15 (45,45%) subyek, dan pembentukan kelenjar submukosa derajat 2 sebanyak 17 (51,51%) subyek. Infiltrasi sel inflamasi dari masing-masing sel (eosinofil, limfosit dan neutrofil) yang terbanyak adalah eosinofil derajat 0 sebanyak 23 (69,69%) subyek, limfosit derajat 2 sebanyak 8 (24,24%) dan neutrofil derajat 0 sebanyak 18 (54,54%) subyek. Simpulan : Terdapat hubungan antara derajat konka hipertrofi dengan sumbatan hidung pada RSK. Tidak terdapat hubungan antara gambaran histopatologi konka hipertrofi (hiperplasia sel goblet; pembentukan kelenjar submukosa; Infiltrasi sel inflamasi : eosinophil, limfosit, neutrofil) dengan sumbatan hidung pada RSK. Kata kunci : Rinosinusitis kronik, konka hipertrofi, sumbatan hidung, kuesioner NOSE, histopatologi
 Karya Umum
Karya Umum 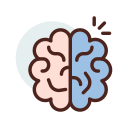 Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial 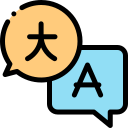 Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 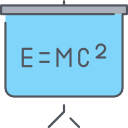 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 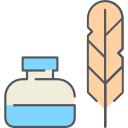 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 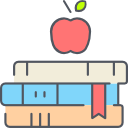 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah