Ditapis dengan

Insidensi infeksi luka operasi tulang belakang pada operasi bedah saraf selama bulan Januari-Desember 2017 di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Indonesia
Pendahuluan: Infeksi Luka Operasi (ILO) sebagai penyebab substansial morbiditas, rawat inap berkepanjangan dan kematian. Jenis prosedur bedah rawat inap yang paling umum adalah prosedur bedah saraf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan insidensi infeksi luka operasi (ILO) dalam prosedur bedah saraf dan menentukan agen etiologi yang paling umum dari infeksi luka operasi di Rumah Sakit Umum Kariadi periode Januari hingga Desember 2017. Metode: Ini adalah penelitian deskriptif-retrospektif. Data dikumpulkan dari rekam medis pasien yang menjalani intervensi bedah saraf di Rumah Sakit Umum Kariadi antara 1 Januari - 31 Desember 2017. Semua responden dengan prosedur bedah saraf yang memenuhi kriteria National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) dari insisi superfisial dan kriteria Hulton dimasukkan. Hasil: Sebanyak 196 pasien menjalani prosedur bedah saraf selama antara 1 Januari - 31 Desember 2017. Dari jumlah tersebut, 15 kasus (7,65%) mengalami infeksi di tempat bedah. Ada 6 kasus wanita dan 9 kasus pria (2: 3). Tingkat kejadian tertinggi adalah pada kelompok usia tua (45-65 tahun). Dalam studi mikrobiologi, kami menemukan beberapa bakteri seperti Acinetobacter baumannii 2 kasus (13,3%), Escherichia coli 4 kasus (26,6%), kasus Enterococcus faecalis 1 (6,6%), kasus Proteus mirabilis 1 (6,6%) ), tanpa bakteri 6 kasus (40%) dan 1 tidak teridentifikasi (6,6%). Diskusi: Infeksi luka operasi sering dan komplikasi serius dari prosedur bedah dan tetap menjadi masalah utama untuk keselamatan pasien. Beberapa prediktor independen ILO umumnya pada orang tua, termasuk kondisi komorbiditas, variabel perioperatif dan faktor sosial ekonomi. Dalam analisis agen etiologi infeksi dalam penelitian ini adalah Escherichia coli. Menurut literatur bahwa patogen yang bertanggung jawab di sebagian besar ILO berasal dari flora endogen pasien, di samping sumber daya eksogen. Penting untuk mengikuti pedoman berbasis bukti untuk pencegahan ILO, mulai dari prosedur pra operasi, perioperatif, dan pasca operasi. Kesimpulan: Kami menemukan 15 kasus infeksi di tempat bedah dalam prosedur bedah saraf dalam periode 1 tahun. Banyak faktor yang terkait dengan pasien dan prosedur yang memengaruhi risiko, dan itu membutuhkan pendekatan komprehensif untuk mencegah kejadian ILO Kata kunci: infeksi luka operasi bedah saraf, infeksi

Hubungan antara angka kejadian fraktur vertebra pada kelompok usia dan etiologi fraktur vertebra yang mendapat perlakuan pada bagian bedah orthopedi RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2014-2018
Latar belakang: Penelitian mengenai angka kejadian fraktur vertebra di Indonesia masih sangat minim, yaitu hanya terdapat 1 penelitian oleh RSUD dr. Soetomo Surabaya. Penelitian di RSUP Dr.Kariadi mengenai kasus fraktur vertebra belum pernah dilakukan walaupun kejadiannya cukup sering. Tujuan: Mengetahui angka kejadian fraktur vertebra berdasarkan usia, jenis kelamin, etiologi, level kerusakan vertebra yang mendapat perlakuan serta hubungan antara angka kejadian fraktur vertebra menurut kelompok usia dan etiologi fraktur vertebra yang mendapat perlakuan pada bagian Bedah Orthopedi RSUP dr. Kariadi Semarang dari tahun 2014-2018 Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi deskriptif dengan analisa retrospektif. Pengumpulan data rekam medis pasien yang terdiagnosis fraktur vertebra berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pencitraan (X ray dan MRI) di RSUP Dr. Kariadi Semarang dan telah mendapat perlakuan. Data tersebut kemudian dianalisa lebih lanjut berdasarkan usia, jenis kelamin, etiologi dan level kerusakan serta hubungan antara usia dan etiologi fraktur vertebra. Hasil: Dari 165 kasus pasien dengan fraktur vertebra yang mendapat perlakuan, Usia tebanyak adalah 41-50 tahun (45 kasus), jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki (102 kasus), kasus terbanyak (72 kasus) disebabkan oleh trauma, dan level terbanyak fraktur terjadi pada vertebra thoracal (91 kasus). Rerata umur pada kelompok etiologi spondylitis TB yaitu 47,87 (15,51) tahun, trauma sebesar 41,94 (13,70) tahun, metastasis sebesar 50,94 (6,82) tahun dan tumor primer sebesar 51,37 (19,29) tahun. Pada uji One-Way Anova didapatkan perbedaan rerata usia bermakna pada setidaknya 1 kelompok etiologi (p = 0,002). Hasil uji post hoc Bonferoni didapatkan perbedaan bermaknarerata usia antar kelompok etiologi spondylitis TB dengan kelompok etiologi metastasis (p-value

Profil test fungsi hati pre operasi terhadap angka keberhasilan operasi kasai di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode tahun 2017-2018
Latar belakang. Angka kejadian atresia bilier semakin meningkat dengan berbagai macam karakteristik profil fungsi hati. Terapi yang masih sering digunakan adalah operasi prosedur kasai dengan berbagai macam outcome pasca operasi. Fungsi hati sering dihubungkan dengan keberhasilan operasi prosedur Kasai Tujuan. Mengetahui karakteristik profil fungsi test hati pre operasi pada pasien dengan atresia bilier yang menjalani operasi prosedur Kasai dan mengetahui gambaran fungsi hati pada outcome paska operasi. Metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi deskriptif observasional. Pengumpulan data rekam medis pasien yang menjalani operasi prosedur Kasai di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Data hasil laboratorium dengan parameter bilirubin direk pre operasi, bilirubin indirek pre operasi, SGOT pre operasi, SGPT pre operasi dikelompokkan sesuai urutan kadar dan dihubungkan dengan outcome paska operasi ascites paska operasi, infeksi pasca operasi, warna feses pasca operasi, dan lama perawatan PICU pasca operasi. Hasil. Dari 20 kasus pasien yang menjalani operasi prosedur Kasai, pada pasien yang mengalami ascites pasca operasi sebanyak 44% memiliki kadar bilirubin direk pre operasi senilai >6 mg/dl. Pasien yang mengalami infeksi pasca operasi 50% memiliki kadar bilirubin direk pre operasi senilai >6 mg/dl, pada pasien dengan warna feses pucat pasca operasi 57,1% memiliki kadar bilirubin direk pre operasi senilai >57,1% dan pada pasien yang dirawat di PICU pasca operasi 62,5% memiliki kadar bilirubin direk pre operasi senilai >6 mg/dl Simpulan. Pasien atresia bilier yang dilakukan operasi prosedur kasai dengan outcome yang buruk mayoritas memiliki parameter laboratorium profil tes hati yang buruk. Risiko outcome yang buruk meningkat seiring dengan meningkatnya kadar bilirubin direk, indirek, SGOT. SGPT dan menurunnya albumin pada hasil laboratorium pre operasi. Kata kunci: Atresia bilier, Kasai Procedure, Bilirubin, SGOT, SGPT, Albumin, LFT, Ascites, PICU Lampiran C2

Perbedaan skor gejala klinis, kualitas hidup dan gambaran endoskopi pasca operasi dengan dan tanpa asam hyaluronat : studi pada pasien rinosinusitas kronik pasca bedah sinus endoskopik fungsional
Latar belakang . Rinosinusitis kronik (RSK) adalah penyakit inflamasi kronik pada mukosa hidung dan sinus paranasal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Pengobatan RSK saat ini dapat dilakukan dengan Bedah Sinus Endoskopik Fungsional (BSEF) dengan harapan dapat mengembalikan fungsi mukosa hidung secara fisiologis. Asam Hyaluronat (AH) dapat mengembalikan pertahanan alami mukosa dan memutuskan proses inflamasi. Tujuan . Mengetahui perbedaan skor gejala klinis, kualitas hidup dan gambaran endoskopi pada pasien RSK pasca BSEF yang diberikan terapi standar ditambah AH dibandingkan tanpa AH. Metode . Penelitian ini adalah penelitian intervensi dengan rancangan penelitian Pre and Post-test randomized control group design dari 50 subjek berupa pasien dengan RSK di Rumah Sakit Umum Propinsi Dr. Kariadi Semarang pada bulan Mei hingga November 2019. Subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol yang diterapi tanpa AH dan kelompok perlakuan yang diberi terapi AH. Subjek dilakukan penilaian gejala klinis, kualitas hidup dan endoskopik pada pre operasi, minggu 1, 2 dan 4 pasca operasi BSEF. Hasil . Penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat perbaikan skor gejala klinis hidung buntu, skor gejala klinis hidung beringus, gambaran endoskopi edema, gambaran endoskopi discaj dan gambaran endoskopi krusta pada pasien RSK pasca BSEF yang diberi terapi standar ditambah AH. Simpulan . Skor gejala klinis hidung buntu, hidung beringus dan gambaran endoskopi edema, discaj dan krusta didapatkan perbedaan bermakna secara klinis antara kelompok perlakuan dibanding kelompok kontrol. Kata Kunci : Rinosinusitis kronis, Asam Hyaluronat, Gejala klinis, kualitas hidup, gambaran endoskopi

Perbedaan jumlah sel inflamasi pada mukosa hidung dan darah tepi pasca operasi dengan dan tanpa asam hyaluronat : studi pada pasien rinosinusitis kronik pasca bedah sinus endoskopik fungsional
Latar belakang: Rinosinusitis kronik (RSK) adalah penyakit inflamasi kronik pada mukosa hidung dan sinus paranasal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Paradigma pengobatan saat ini bergantung pada bedah sinus endoskopi fungsional (BSEF) dengan harapan bahwa mukosa sakit dapat diperbaiki sehingga kembali ke keadaan fisiologis. Asam Hyaluronat (AH) dapat mengembalikan pertahanan alami mukosa dan dapat memutus kaskade inflamasi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan jumlah sel inflamasi pada histopatologi mukosa hidung pasien rhinosinusitis kronik pasca Bedah Sinus Endoskopi Fungsional (FESS) yang diberikan terapi standar ditambah asam hyaluronat dibandingkan dengan terapi standar tanpa asam hyaluronat. Metode: Penelitian ini adalah penelitian intervensi dengan rancangan penelitian Pre and Post-test randomized control group design dari 22 pasien RSK (9 laki-laki, 13 perempuan; usia rata-rata 30,95 ± 12,66 tahun; kisaran 18 hingga 55 tahun) di Rumah Sakit Umum dr. Kariadi pada bulan Mei hingga September 2019. Subjek dibagi menjadi dua kelompok: Kelompok perlakuan mendapat terapi AH dan kelompok kontrol tanpa AH. Semua pasien dilakukan biopsi konka inferior dan pemeriksaan darah tepi pada saat operasi dan 4 minggu setelah operasi. Jumlah sel neutrofil, eosinofil, dan limfosit sebelum dan sesudah perlakuan dibandingkan antara dua kelompok. Rasio neutrofil-limfosit (NLR) dan rasio eosinofil-limfosit (ELR) dihitung dan dibandingkan antara dua kelompok. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon. Hasil: Saat kelompok perlakuan dan kontrol, pretest dan posttest dibandingkan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok selain pada perbandingan ELR pada kelompok perlakuan (p: 0,028). Simpulan: Terdapat penurunan ELR pada mukosa konka inferior yang secara statistik signifikan. Level NLR juga menurun namun secara statistik tidak signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian AH topikal dapat memodulasi respons inflamasi secara positif. Kata kunci: Rinosinusitis kronik, FESS, histopatologi, neutrofil, eosinofil, limfosit

Hubungan lama waktu pasca kemoradiasi dengan derajat disfagia orofaringeal pada karsinoma nasofaring
Latar belakang : Disfagia dapat sebagai efek samping pada penderita karsinoma nasofaring (KNF) yang menjalani terapi kemoradiasi. Angka kejadian yang dilaporkan mencapai 83%. Hubungan antara lama waktu pasca kemoradiasi dengan derajat disfagia orofaringeal pada KNF sampai saat ini belum diketahui secara jelas. Tujuan : Menganalisis hubungan lama waktu pasca kemoradiasi dengan derajat disfagia orofaringeal pada KNF. Metode : Penelitian observasional analitik dengan desain belah lintang. Subjek adalah penderita KNF pasca kemoradiasi di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang memenuhi kriteria penelitian. Penentuan status disfagia dan derajat disfagia dengan pemeriksaan Gugging Swallowing Screen (GUSS). Data lengkap subjek didapatkan dari anamnesis dan rekam medis. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-Squared. Hasil : Sebanyak 55 subjek KNF mengalami disfagia (100%), 48 (87,3%) subjek mengalami disfagia derajat ringan, tidak didapatkan subjek yang mengalami disfagia derajat sedang, dan 7 (12,7%) subjek mengalami disfagia derajat berat. Lama waktu pasca kemoradiasi (p = 0,451), jenis kemoterapi (p = 0,267), dan modalitas terapi (p = 0,402) tidak berhubungan dengan derajat disfagia orofaringeal pada KNF. Kesimpulan : Mayoritas subjek terjadi disfagia derajat ringan. Lama waktu pasca kemoradiasi, jenis kemoterapi, dan modalitas terapi tidak berhubungan dengan derajat disfagia orofaringeal pada KNF. Kata Kunci : KNF, kemoradiasi, derajat disfagia, GUSS.

Pengaruh ekstrak daun moringa oleifera oral terhadap ekspresi TNF-Alfa pada retina tikus wistar model glaukoma
Pendahuluan : TIO tinggi pada glaukoma dapat memicu neuroinflamasi pada retina. Neuroinflamasi yang terjadi terus menerus menyebabkan kematian dan kerusakan sel ganglion retina. TNF-α merupakan salah satu mediator inflamasi yang berperan pada neuroinflamasi. Ekstrak daun Moringa oleifera dikenal memilki efek antiinflamasi melalui kemampuannya dalam menekan NFkB, yang merupakan faktor transkripsi mediator inflamasi pada sel glia di retina. Tujuan : Mengetahui pengaruh ekstrak daun Moringa oleifera oral terhadap ekspresi TNF-α di retina tikus Wistar model glaukoma. Metode : Tikus Wistar model glaukoma dibagi kedalam 2 kelompok. Kelompok perlakuan diberi ekstrak daun Moringa oleifera oral dosis 300mg/kgBB/hari selama 4 minggu. Dilakukan pengecatan imunohistokimia pada retina tikus tersebut. Perbedaan antara ekspresi TNF-α paska perlakuan antara kedua kelompok dinilai secara statistik. Signifikan berbeda apabila p < 0.005. Hasil : Rerata skor Allred pengecatan imunohistokimia TNF-α pada kelompok kontrol ( K ) adalah 5,57 ± 0,79; pada kelompok perlakuan ( P ) 5,43 ± 0,54. Hasil uji beda ekspresi TNF-α antara dua kelompok dengan uji Mann Whitney tidak berbeda bermakna ( p > 0,05 ). Kesimpulan : Ekspresi TNF-α pada retina tikus Wistar model glaukoma yang diberi ekstrak daun Moringa oleifera oral lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol meski perbedaan tersebut tidak signifikan Kata Kunci : Moringa oleifera, glaukoma, TNF-α

Kadar galectin 3 vitreus pada tractional retinal detachment dibandingkan dengan rhegmatogen retinal detachment
Latar belakang: Ablasio retina adalah kondisi terpisahnya sel kerucut dan batang dari lapisan epitel pigmen retina yang dapat menyebabkan gangguan fungsi menetap. Fibrosis pada vitreoretinal akibat diabetes merupakan patogenesis utama tractional retinal detachment (TRD), sedangkan patogenesis rhegmatogen retinal detachment (RRD) umumnya terjadi akibat proses degenerasi terkait usia. Penelitian terkait Galectin-3, suatu mediator penting fibrosis jaringan, belum pernah dilakukan pada cairan vitreus. Tujuan: Mengamati ada tidaknya perbedaan kadar Galectin-3 pada cairan vitreus antara penderita TRD dan RRD Metode: Penelitian belah lintang ini mengambil subjek penderita TRD dan RRD yang menjalani operasi di RSUP Dr Kariadi Semarang pada bulan Juli-Agustus 2019. Usia, jenis kelamin, dan kadar galectin-3 dikumpulkan. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis profil demografi. Perbedaan kadar galectin-3 antar kelompok dinilai dengan uji t-tidak berpasangan atau Mann-Whitney. Korelasi antar variabel dinilai dengan uji korelasi Pearson atau Spearman. Hasil: Dua puluh dua pasien dilibatkan dalam penelitian; 54.5% adalah perempuan dan 45.5% laki-laki. Rerata usia didapatkan lebih tua pada kelompok TRD dibandingkan RRD (47,27±5.73 vs 42.00±12.55 tahun, p=0.399). Rerata kadar Galectin-3 didapatkan lebih tinggi pada kelompok TRD dibandingkan RRD (4.09±2.81 vs 0.26±0.14, p

Hubungan hasil pemeriksaan flash dan pattern visual evoked potential terhadap derajat ambliopia pada anak ambliopia
Pendahuluan: Ambliopia adalah turunnya tajam penglihatan terbaik pada satu atau kedua mata tanpa disertai kelainan struktur mata maupun pada jalur visual. Selama ini derajat ambliopia ditentukan dari hasil pemeriksaan subjektif yaitu BCVA. Berdasarkan stimulusnya Visual Evoked Potential (VEP) dibagi menjadi 2, flash dan pattern VEP. Tujuan: Membuktikan hubungan hasil pemeriksaan flash dan pattern VEP terhadap derajat ambliopia pada anak ambliopia refraktif. Metode: Penelitian observasional analitik dengan studi cross-sectional. Sebanyak 36 anak usia 4-15 tahun dengan masing-masing derajat ambliopia refraktif 12 sampel. Latensi dan amplitudo VEP dinilai dengan alat ukur Roland Reti (Model ISXEV 60, Germany). Data dianalisis dengan Uji Kruskal Wallis, Uji Post Hoc Mann Whitney U Test dan Uji Korelasi Spearman. Hasil: Rerata latensi flash VEP (107.13 ±5.59 & 129.74 ±16.63) dan latensi pattern VEP (120.15 ±7.21 & 128.84 2.64) ambliopia ringan dan berat berbeda signifikan (P=0,001, P=0,011). Pada rerata amplitudo flash VEP (7.09 ±2.32 & 4.24 ±1.18) dan amplitudo pattern VEP (7.24 ± 2.23 & 3.97 ± 2.07) ambliopia ringan dan berat berbeda signifikan (P= 0.001, P=0,002). Korelasi negatif signifikan pada amplitudo flash dan pattern VEP (r=-0,465, P

Pengaruh lama paparan prednisolon asetat topikal terhadap matriks ekstra selluler trabecular meshwork tikus wistar
Pendahuluan. Trabecular meshwork adalah serangkaian berkas fenestrasi dan lembaran matriks ekstraseluler yang dilapisi dengan sel endotel, yang berbatasan dengan kanalis Schlemm, dan berfungsi mengatur aliran humor aquous. Prednisolon dilaporkan menyebabkan glaucoma, tetapi belum ada penelitian tentang lama paparan topikal yang dapat menyebabkan perubahan ketebalan matriks ekstraceluler trabecular meshwork. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh lama paparan predisolon asetat topikal terhadap ketebalan matriks ekstraseluler trabecular meshwork dari tikus Wistar. Metode. Penelitian eksperimen dengan desain posttest only controlled group design. Sebanyak 36 tikus dibagi menjadi 6 kelompok, 3 kelompok kontrol (air mata buatan 4 kali sehari) dan 3 kelompok perlakuan (prednisolon asetat 4 kali sehari) yang diamati selama 2,4 dan 6 minggu. Ketebalan matriks ekstraseluler trabecular meshwork dinilai menggunakan skor histopatologi. Data dianalisis dengan Uji Mann Whitney. Hasil. Pada paparan selama 2 minggu tidak terjadi penebalan matriks ekstraseluler trabecular meshwork, (p> 0,05). Paparan 4 minggu 4 terjadi penebalan ringan, 1 penebalan sedang, dan 1 penebalan berat, (p
 Karya Umum
Karya Umum 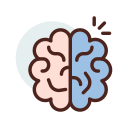 Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial 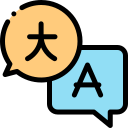 Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 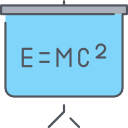 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 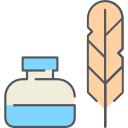 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 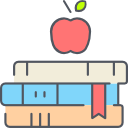 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah