Ditapis dengan

Pengaruh waktu pelayanan anestesi terhadap tingkat utilisasi di Instalasi Bedah Sentral RSUP Dr. Kariadi Semarang
Latar belakang: Kamar operasi di sebuah rumah sakit merupakan fasilitas yang sangat penting. Salah satu tolok ukur apakah kamar operasi berfungsi dengan baik adalah utilisasi yang didefinisikan sebagai hasil bagi dari waktu yang benar-benar digunakan selama jam efektif dan jumlah dari jam efektif yang tersedia untuk digunakan. Utilisasi optimal bisa dicapai dengan catatan toleransi keterlambatan operasi masing-masing tidak lebih dari 15 menit dan waktu turn over dijaga seminimal mungkin. Dalam waktu turn over terdapat peran pelayanan anestesi berupa persiapan pembiusan, pelaksanaan pembiusan dan pasca operasi sebelum pasien ditransfer ke ruang post anesteshia care unit (PACU) atau ruang pemulihan. Sehingga dengan mengoptimalkan waktu pelayanan anestesi diharapkan dapat meminimalkan waktu turn over dan memaksimalkan utilisasi. Tujuan: Mengetahui pengaruh waktu pelayanan anestesi terhadap tingkat utilisasi di IBS RSUP Dr. Kariadi Semarang. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional. Dengan mengambil data retrospektif berupa pencatatan waktu pelaksanaaan operasi elektif selain operasi dengan lokal anestesi, bedah jantung, dan bedah sehari selama tiga bulan periode Januari – Maret 2017 di Instalasi Bedah Sentral RSUP Dr. Kariadi Semarang pada hari kerja efektif Senin – Jumat, tidak termasuk hari libur tanggal merah. Data yang diambil adalah waktu aktual pelaksanaan operasi dan waktu turn over selama 24 jam. Dari data tersebut akan dihitung angka utilisasi dan waktu pelayanan anestesi kemudian dengan uji beda statistik akan dibandingkan antara dua periode waktu yang berbeda yaitu pukul 08.00 – 18.00 dan 18.00 – 07.00. Hasil akhir akan dianalisis pengaruh waktu pelayanan anestesi terhadap utilisasi kamar operasi di IBS RSUP Dr. Kariadi Semarang. Hasil: Utilisasi di Instalasi Bedah Sentral RSUP Dr. Kariadi Semarang dalam waktu 24 jam berada pada kategori rata-rata dengan nilai 56,73%. Namun, dalam dua periode waktu (08.00 – 18.00 dan 18.00 – 07.00) menjadi berbeda bermakna (p 15 menit. Kata kunci: waktu pelayanan anestesi, waktu turn over, utilisasi.

Validitas SASA (Surgical Apgar Score & ASA) terhadap morbiditas dan mortalitas pasca operasi kraniotomi RSUP Dr. Kariadi Semarang
Latar belakang: Operasi kraniotomi memiliki resiko yang besar terjadinya morbiditas dan mortalitas di RSUP dr. Kariadi Semarang. Studi prognostik dapat memberi prediksi yang akurat dan bermanfaat bagi pasien. SASA (Surgical Apgar Score & ASA) merupakan salah satu metode yang menggabungkan status ASA merupakan cermin status pasien pra operasi, dan SAS mencerminkan status pasien intraoperatif yang berdasarkan pada tiga parameter fisiologis yang mudah dihitung: perkiraan jumlah kehilangan darah, denyut jantung (HR) terendah, dan tekanan arteri rerata (MAP) terendah selama periode intra-operatif. SASA juga bermanfaat dalam prediksi morbiditas pasca operasi bedah saraf selain kematian Tujuan : Mengetahui hubungan antara SASA (Surgical Apgar Score & ASA) dengan kejadian morbiditas dan mortalitas pasca operasi pasien kraniotomi di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cohort prospektif Total sampel pasien bedah saraf yang menjalani kraniotomi pada bulan Oktober 2017 adalah sebesar 62 pasien. 37 pasien memenuhi kriteria inklusi. Karakteristik pasien kemudian dikelompokkan menjadi jenis kelamin, dan kelompok umur. Kemudian diikuti selama proses operasi lalu dicatat skor SASA, morbiditas dan mortalitas yang terjadi pasca operasi dan selama perawatan. Untuk melihat hubungan SASA dengan morbiditas dan mortalitas di uji dengan pearson chi square test Hasil : Pada penelitian ini didapatkan mortalitas pasca operasi sebanyak 18,9 %. Sebanyak 15 (40,5%)pasien memiliki morbiditas dan mortalitas selama perawatan dengan komplikasi terbanyak adalah perdarahan yang membutuhkan 2 unit transfusi sel darah merah dalam waktu 72 jam diikuti dengan koma selama 24 jam post operasi. Setelah stratifikasi SASA, 18 (48,6%) pasien dikategorikan sebagai resiko sedang dengan nilai mean SASA, 12,56 ± 1,65, pasien resiko rendah sebanyak 12 (32,4%) dengan nilai mean SASA 15,67 ± 0,99 dan 7 (18,9%) pasien adalah resiko tinggi dengan nilai mean SASA 7,29 ± 0,76). Dari keseluruhan 15 pasien yang mendapatkan morbiditas dan mortalitas, pada kelompok resiko rendah tidak ada morbiditas dan mortalitas sedangkan pada kelompok resiko tinggi semua mengalami mobditas dan mortalitas dengan hasil berbeda bermakna ( P = 0,000) Simpulan : Skor SASA memiliki korelasi bermakna dengan kejadian morbiditas atau mortalitas. Pada kelompok resiko tinggi (skor 2 – 8) semua mengalami mobditas dan mortalitas dan sebaliknya pada skor SASA kelompok resiko rendah (skor 15 – 20) tidak didapatkan morbiditas dan mortalitas Kata kunci : SASA, kraniotomi, morbiditas, mortalitas

Perbandingan efektifitas antara patient controlled analgesia (PCA) ketamin dengan continous infusion analgesia(CIA) ketamin pada pengelolaan nyeri pasca operasi Modified Radical Mastectomy (MRM)
Latar Belakang : Efektivitas kontrol nyeri pasca bedah sekarang telah menjadi aspek esensial dalam perawatan perioperatif, sehingga kini banyak rumah sakit telah mempunyai unit tersediri untuk pelayanan nyeri pasca bedah (acute pain service). Ketamin merupakan salah satu obat pilihan dalam manajemen nyeri. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk kontrol cepat terhadap nyeri adalah menggunakan Patient Contolled Analgesia (PCA). PCA memungkinkan pasien untuk memiliki satu set dosis yang tersedia sesuai kebutuhan dalam menangani nyeri sesegera mungkin. Hal inilah yang menjadi kelebihan penggunaan Patient Controlled Analgesia (PCA). Tujuan :. Mengevaluasi efektivitas Patient-controlled analgesia (PCA) dengan menggunakan regimen ketamin dibandingkan dengan continuous infusion analgesia (CIA) dengan regimen ketamin sebagai pengelolaan nyeri pasca operasi MRM. Metode : Dilakukan uji klinis acak tersamar tunggal terhadap 24 pasien rencana operasi MRM yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah dilakukan anestesi umum, pasien dibagi dalam 2 kelompok perlakuan pemberian analgetik pasca operasi: 1) kelompok PCA Ketamin dengan ketamin loading dose 0,5 mg/kgBB, demand dose 0,3 mg/kgBB, lockout interval 10 menit, limit dose 6 x demand dose; 2) kelompok CIA ketamin loading ketamin loading dose 0,5 mg/kgBB, dilanjutkan dengan maintenance dose 0,3 mg/kgBB/jam. Dilakukan penilaian berkala skorNRS, RASS, efek samping dan tingkat kepuasan pasien selama 24 jam pasca operasi. Data dianalisa dengan Shapiro-Wilk dilanjutkan dengan Mann Whitney atau dengan uji T, dianggap bermakna bila p< 0,05. Hasil : Penggunaan PCA ketamin sebagai analgetik pasca operasi MRM sama efektif dengan CIA ketamin, namun PCA ketamin lebih efisien dalam hal penggunaan obat bila dibandingkan dengan CIA. Tingkat kepuasan pasien yang menggunakan PCA ketamin dan CIA ketamin sebagai analgetik pasca operasi MRM tidak menunjukan perbedaan yang bermakna. Efek samping mual, muntah dan nyeri kepala yang terjadi antara perlakuan PCA ketamin dan CIA ketamin sebagai analgetik pasca operasi MRM tidak menunjukan perbedaan yang bermakna. Kata Kunci : MRM, PCA ketamin, CIA ketamin, NRS, RASS, efek samping, tingkat kepuasan pasien.

Perbandingan durasi ventilasi mekanik pasien pasca bedah dengan ventilator antara sedasi midazolam atau propofol di ICU RSUP Dr. Kariadi
Latar Belakang: Sedasi di ruang intensif dapat memperbaiki outcome perawatan dan membuat pasien lebih nyaman, namun juga berpotensi memperpanjang durasi ventilasi mekanik dan length of stay (LOS). Obat yang saat ini sering digunakan adalah midazolam, namun durasi kerja midazolam dapat memanjang pada pasien dengan gagal fungsi organ. Propofol adalah obat sedasi dengan klirens tinggi dan tanpa metabolit aktif yang dapat digunakan untuk memperpendek durasi ventilasi mekanik dan LOS pasien. Tujuan: Membandingkan durasi ventilasi mekanik dan biaya sedasi pada pasien pascabedah di ruang intensif yang disedasi menggunakan midazolam dan propofol. Metode: Dilakukan penelitian observasional dengan desain cross-sectional terhadap 30 pasien pascabedah dengan ventilator di ICU yang dibagi menjadi 2 kelompok secara acak, masing-masing kelompok terdiri dari 15 pasien. Kelompok I mendapat midazolam bolus 0,02-0,08 mg/kg IV, dilanjutkan infus kontinyu dosis 0,04-0,2 mg/kg/jam. Kelompok II mendapat Propofol bolus 1,5-2,5 mg/kg IV, dilanjutkan infus kontinyu dosis 5-80 μg/kg/menit. Target skor RASS adalah -1 sampai -2, yang dipantau 1 jam pascasedasi, dilanjutkan tiap 4 jam setelahnya. Pencatatan dilakukan terhadap durasi ventilator mekanik, rerata skor RASS, dan biaya sedasi. Hasil: Penelitian ini menunjukan bahwa durasi ventilasi mekanik dan biaya sedasi pada kelompok propofol lebih rendah daripada midazolam, namun perbedaannya tidak bermakna dengan nilai p≤0,05. Kesimpulan: Sedasi pasien pascabedah dengan ventilator di ruang intensif dengan propofol lebih efektif dalam mengurangi durasi ventilasi mekanik dan biaya sedasi daripada midazolam, namun tidak berbeda bermakna. Kata Kunci : Propofol, midazolam, sedasi, ICU, durasi ventilasi mekanik, biaya sedasi

Perbandingan efektivitas Patient Controlled Analgesia (PCA) fentanil, PCA morfin dan tramadol intravena sebagai analgetik pasca operasi Modified Radical Mastectomy (MRM)
Latar Belakang : Operasi Modified Radical Mastectomy menimbulkan nyeri derajat sedang hingga berat pasca operasi. Sebagian pasien yang mendapat analgetik bolus berkala tramadol ketorolak masih mengeluh nyeri. PCA merupakan metode baru pemberian analgetik. Penggunaan PCA fentanil dan PCA morfin diharapkan dapat lebih efektif dalam pengelolaan nyeri pasca operasi MRM. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas, efek samping dan tingkat kepuasan pasien antara penggunaan PCA fentanil, PCA morfin dan tramadol intravena sebagai analgetik pasca operasi MRM. Metode : Dilakukan uji klinis acak tersamar ganda terhadap 36 pasien rencana operasi MRM yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah dilakukan anestesi umum, pasien dibagi dalam 3 kelompok perlakuan pemberian analgetik pasca operasi: 1) kelompok PCA fentanil dengan fentanil loading dose 50 mcg, demand dose 20 mcg, lockout interval 10 menit, limit dose 70 mcg/jam, background infusion 30 mcg/jam; 2) kelompok PCA morfin dengan morfin loading dose 4 mg, demand dose 1 mg, lockout interval 10 menit, limit dose 6 mg/jam, tanpa background infusion; 3) kelompok tramadol yang mendapat tramadol intravena 100 mg/8jam. Dilakukan penilaian berkala skor NRS, RAAS, tanda vital, efek samping dan tingkat kepuasan pasien selama 24 jam pasca operasi. Data dianalisa dengan Shapiro-Wilk dilanjutkan Kruskal-Wallis atau ANOVA, dianggap bermakna bila p< 0,05. Hasil : Efektivitas terbaik pada PCA fentanil, diikuti PCA morfin lalu tramadol. Skala sedasi kelompok PCA fentanil dan PCA morfin lebih dalam dari kelompok tramadol pada jam ke-0. Tidak terjadi hipotensi, bradikardi ataupun depresi napas pada semua kelompok. Terdapat efek samping mual, muntah dan dizziness namun secara statistik tidak berbeda bermakna. Tingkat kepuasan pasien tertinggi pada kelompok PCA fentanil. Tingkat kepuasan pasien kelompok PCA morfin dan tramadol tidak berbeda bermakna. Tekanan darah, laju napas dan laju nadi kelompok PCA fentanil dan PCA morfin lebih rendah daripada tramadol. Kata Kunci : MRM, PCA fentanil, PCA morfin, tramadol, efektivitas, efek samping, tingkat kepuasan pasien.

Perbandingan pemakaian triclosan 0,3% dan chlorhexidine 0,2% untuk oral Hygiene terhadap kejadian ventilator associated pneumonia di ICU RSUP dr. Kariadi Semarang
Latar Belakang: Pembersihan mulut (oral hygiene) pasien di ICU diperlukan untuk menjaga kondisi flora normal pasien kritis.Antiseptik oral hygiene merupakan salah satu cara non farmakologi yang dapat menurunkan insiden ventilator Associated Pneumonia (VAP) dengan menurunkan skor Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) pada ventilator mekanik.Center for Disease Control (CDC) menyatakan bahwa Perawatan oral hygiene yang baik dapat mengurangi angka kejadian Ventilator Assosiated Pneumonia (VAP) sampai 60%. Chlorhexidine dan Triclosan adalah antiseptik yang mampu membunuh dan mencegah pertumbuhan bakteri. Tujuan: Mengetahui perbedaan pengaruh Triclosan 0,3% dan Chlorheksidin 0,2% sebagai agen oral hygiene terhadap kejadian VAP pasien ICU Metode: Desain eksperimental, 20 Subjek dibagi dua kelompok memenuhi kriteria inklusi sama besar (n=10). Kelompok chlorheksidin 0,2% dan kelompok kontrol triclosan 0,3%. Kedua kelompok sebelum dan sesudah perlakuan dilakukan pemeriksaan CPIS; suhu, leukosit darah, sekret trakea, PaO2/FiO2, dan radiologi dada. Uji homogenitas sampel usia dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada kelompok triclosan dan chlorheksidin.Uji normalitas untuk distribusi data dilanjutkan uji beda dengan Mann Whitney. Hasil: Menurut data sampel uji homogenitas didapatkan nilai P= 0,555 pada triclosan dan P=0,224 pada chlorheksidin, dimana nilai P≥0,05 atau tidak berbeda bermakna. Data dilanjutkan uji normalitas dengan hasil pada kelompok triclosan nilai P=0,149 atau P ≥0,05 dan kelompok chlorheksidin nilai P=0,004 atau P ≤0,05. Berdasarkan hasil Uji Shapiro wilk didapatkan salah satu hasil nilai P tidak normal pada triclosan. Dilanjutkan uji beda dengan uji komparatif menggunakan uji non parametrik Mann-whitney dengan hasil nilai P=0,310 atau P≥0,05. Artinya tidak berbeda bermakna antara pengaruh pemberian triclosan dan chlorheksidine sebagai oral hygiene dalam pencegahan terhadap kejadian VAP. Kesimpulan: Pemberian triclosan 0,3% sebagai oral hygiene terbukti efektifitasnya sama dengan chlorheksidin 0,2% untuk mencegah kejadian VAP di ICU. Kata Kunci: Triclosan 0,3%, chlorhesidin 0,2%, Oral hygiene, Ventilator Assosiated Pneumonia (VAP), Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS ).

Menilai perbedaan Mortality Rate pasien sepsis pada pemeriksaan ratio neutrofil limfosit dan sequential organ failure assesment (SOFA) skor di ruang ICU RSUP Dr. Kariadi
Latar belakang : sepsis merupakan penyebab utama kematian dari kasus infeksi, terutama bila tidak diketahui sejak awal atau terlambat terapi. Infeksi bakteri yang berkembang menjadi sepsis merupakan suatu respon tubuh terhadap invasi mikroorganisme, bakteremia atau pelepasan sitokin akibat pelepasan endotoksin oleh bakteri gram negatif atau gram positif. Ratio neutrofil limfosit (RNL) memiliki peranan sebagai prediktor bakteremia dan dapat memprediksi kondisi infeksi bakteri. Morbiditas dan mortalitas di ICU ditentukan oleh perkembangan kegagalan fungsi organ yang terjadi. Kerusakan dan kegagalan fungsi organ ini dapat dimonitor antara lain dengan menggunakan Sequential Organ Failure Assesment (SOFA) skor. Jumlah skor SOFA rata-rata pada 48 jam pertama merupakan indikator prognosis yang cukup baik untuk keluaran pasien. Tujuan : Apakah terdapat perbedaan mortality rate pasien sepsis berdasarkan pemeriksaan Ratio Neutrofil Limfosit sebagai biomarker sederhana penanda sepsis dan Skor Sequential Organ Failure Assesment (SOFA) sebagai predictor mortality di ruang ICU RSUP dr. Kariadi Metode : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional. Besar sampel yang didapatkan sebanyak 32 pasien yang masuk kriteria inklusi dengan metode total sampling. Pasien yang masuk perawatan ICU dan memenuhi kriteria inklusi dilakukan perhitungan RNL dan SOFA dengan cara pengambilan darah pada jam 0, jam 24 dan jam 48. Parameter pengambilan darah termasuk darah rutin serta darah tepi, fungsi hepar (bilirubin direk, bilirubin indirek dan bilirubin total), fungsi ginjal (ureum, kreatinin), analisa gas darah. Data di analisa menggunakan uji anova dan uji interclass correlation coeficient untuk menilai reabilitas 2 arah. Hasil : Ratio neutrofil limfosit dapat di hubungkan dengan tingkat keparahan pada pasien sakit kritis. Pada pasien dengan sepsis, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara ratio neutrofil limfosit dan mortalitas. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman tentang patofisiologi dan hubungan RNL terhadap mortalitas untuk melengkapi penelitian ini. Kesimpulan : RNL dapat dijadikan prediktor outcome mortality rate pada pasien sepsis yang di rawat di ruang ICU. Penilaian RNL dapat menunjukkan beratnya kegagalan organ pada pasien sepsis yang di rawat di ruang ICU. Penilaian RNL memiliki korelasi dengan mortality rate berdasarkan SOFA skor pada pasien sepsis yang dirawat di ruang ICU Kata kunci : Sepsis, Ratio neutrofil limfosit, Sequential organ failure assesment

Perbandingan efektivitas Patient Controlled Analgesia (PCA) ketamin, PCA morfin dan traadol intravena sebagai analgetik pasca operasi Modified Radical Mastectomy (MRM)
Latar Belakang : Operasi Modified Radical Mastectomy menimbulkan nyeri derajat sedang hingga berat pasca operasi. Sebagian pasien yang mendapat analgetik bolus berkala tramadol ketorolak masih mengeluh nyeri. PCA merupakan metode baru pemberian analgetik. Penggunaan PCA ketamin dan PCA morfin diharapkan dapat lebih efektif dalam pengelolaan nyeri pasca operasi MRM. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efektivitas, efek samping dan tingkat kepuasan pasien antara penggunaan PCA fentanil, PCA morfin dan tramadol intravena sebagai analgetik pasca operasi MRM. Metode : Dilakukan uji klinis acak tersamar ganda terhadap 36 pasien rencana operasi MRM yang memenuhi kriteria penelitian. Setelah dilakukan anestesi umum, pasien dibagi dalam 3 kelompok perlakuan pemberian analgetik pasca operasi: 1) kelompok PCA ketamin dengan loading dose 0,5 mg/kgBB, demand dose 0,3 mg/kgBB, lockout interval 10 menit, limit dose 6x demand dose, background infusion tidak diberikan; 2) kelompok PCA morfin dengan loading dose 0,05 mg/kgBB, demand dose 0,03 mg/kgBB, lockout interval 10 menit, limit dose 6x demand dose, background infusion tidak diberikan; 3) kelompok tramadol yang mendapat tramadol intravena 100 mg/8jam. Dilakukan penilaian berkala skor NRS, RAAS, tanda vital, efek samping dan tingkat kepuasan pasien selama 24 jam pasca operasi. Data dianalisa dengan Shapiro-Wilk dilanjutkan Kruskal-Wallis atau ANOVA, dianggap bermakna bila p< 0,05. Hasil : Efektivitas tertinggi didapatkan pada kelompok PCA ketamin kemudian PCA morfin dan tramadol. Tidak ada perbedaan bermakna terhadap kepuasan pasien pada ketiga kelompok perlakuan baik PCA ketamin, PCA morfin, dan tramadol intravena. Walaupun kelompok PCA ketamin memiliki nilai rata-rata kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok PCA morfin dan tramadol intravena. Skala nyeri kelompok PCA ketamin adalah yang paling rendah diikuti dengan PCA morfin, sedangkan skala nyeri yang tertinggi didapatkan pada kelompok tramadol intravena. Kata Kunci : MRM, PCA ketamin, PCA morfin, tramadol, ketorolak, NRS, RAAS, efek samping, tingkat kepuasan pasien.

Perbandingan kadar neutrofil pada epidural analgesia antara bupivakain isobarik 0,25% dengan adjuvant fentanyl 0,05 MG dan bupivakain isobarik 0,125% dengan adjuvant fentanyl 0,05 MG pada pasien yang menjalani bedah abdomen
Latar Belakang : Laparotomi merupakan salah satu prosedur pembedahan mayor dengan cara melakukan penyayatan pada lapisan dinding abdomen untuk mendapatkan organ dalam abdomen yang mengalami masalah. Trauma akibat pembedahan merupakan suatu stres fisik dan psikologis yang dikaitkan dengan perubahan neuroendokrin, metabolik, dan sistem imun. Epidural analgesia dapat mempengaruhi respon imun perioperatif dan mengurangi kemoatraktan neutrofil pada jaringan yang mengalami trauma. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menilai efek bupivakain 0,25% dengan adjuvant fentanil 0,05mg dan bupivakain 0,125% dengan adjuvant fentanil 0,05mg sebagai analgesia epidural terhadap kadar neutrofil pada operasi abdomen terbuka dengan membandingkan kadar neutrofil antarakelompok I dan kelompok II pada saat sebelum tindakan epidural dan 4 jam pasca bedah. Metode : Dilakukan penelitian eksperimental dengan rancangan randomized, double-blind, controlled trial. Besar sampel berjumlah 25 sampel tiap kelompok. Penderita yang memenuhi kriteria penelitian menjalani prosedur persiapan operasi elektif. Dilakukan pengambilan sampel darah vena untuk pemeriksaan kadar neutrofil pada saat sebelum pemasangan epidural dan 4 jam pascabedah. Loading dose dan maintenans pada kelompok I menggunakan bupivakain 0,25% dengan adjuvant fentanil 0,05mg via kateter epidural dengan volume sesuai perhitungan, sedangkan padakelompok II menggunakan bupivakain 0,125% dengan adjuvant fentanil 0,05mg. Data dianalisa secara statistik menggunakan uji Mann Whitney U, dianggap bermakna bila p< 0,05. Hasil : Tidak ada perbedaan secara statistik kadar neutrofil antara kelompok I dengan kelompok II pada semua waktu pengukuran. Sehingga disimpulkan bahwa bupivakain 0,25% dengan adjuvant fentanil 0,05mg memberikan efek yang sama dengan bupivakain 0,125% dengan adjuvant fentanil 0,05mg sebagai analgesia epidural dalam mempertahankan kadar neutrofil dalam rentang nilai normal (p=0,775). Kata Kunci : Inflamasi, Neutrofil, Epidural, Bupivakain, Operasi abdomen

Kejadian kurang pendengaran tipe sensorik neonatus preterm yang mengalami asfiksia pada skrining awal pendengaran
Latar belakang. Prevalensi kurang pendengaran di Indonesia tahun 2013 pada usia ≥ 5 tahun sebesar 2,6%. Asfiksia dan BBLSR merupakan faktor risiko yang dipaparkan oleh Joint Committee on Infant Hearing. Beberapa studi menyatakan bahwa skor Apgar yang rendah pada bayi preterm lebih menggambarkan imaturitas dibanding dampak dari gawat janin. Tujuan. Menganalisis pengaruh asfiksia pada neonatus preterm terhadap kejadian kurang pendengaran tipe sensorik berdasarkan skrining awal pendengaran. Metode. Penelitian kohort. Subyek: neonatus preterm dengan riwayat asfiksia sedang dan berat dirawat di RSUP dr. Kariadi Semarang bulan Januari 2016 – Juni 2017, dipilih secara consecutive sampling, sesuai criteria inklusi dan eksklusi. Kurang pendengaran sensorik (KPS) ditentukan dari pemeriksaan Otoacoustic emission (OAE) yang dilakukan saat pulang perawatan dan usia 3 bulan. Analisis dilakukan dengan uji Chi-square, t-test, dan Mann-Whitney. Hasil. Dari 73 bayi yang dilakukan follow up, OAE I menunjukkan 32 bayi refer dan 41 bayi pass. Skor Apgar menit ke-1 ≤ 3 bukan merupakan faktor risiko KP sensorik pada neonatus preterm dengan asfiksia. Usia gestasi < 32 minggu dan BBLSR meningkatkan risiko KP sensorik (masing-masing OR 3,8; 95% IK 1,29-11,09,p 0,01 dan OR 3,9; 95% IK 1,47-10,81, p 0,005). Usia gestasi < 32 minggu dan BBLSR secara bersama-sama bukan merupakan faktor risiko KP sensorik pada neonatus preterm dengan asfiksia dari pemeriksaan OAE I. Simpulan. Skor Apgar menit ke-1 ≤ 3 tidak mempengaruhi KPS dari skrining awal pendengaran pada neonatus preterm dengan asfiksia. Usia gestasi < 32 minggu dan BBLSR secara individual meningkatkan risiko KPS pada neonatus preterm dengan asfiksia. Kata kunci : OAE, kurang pendengaran sensorik, asfiksia, preterm
 Karya Umum
Karya Umum 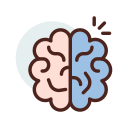 Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial 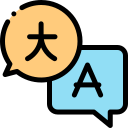 Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 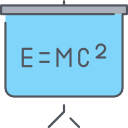 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 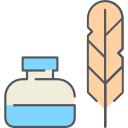 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 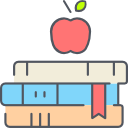 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah