Ditapis dengan

Gambaran radiologi usia tulang dan kadar hormon para tiroid pada anak dengan penyakit ginjal kronik
Latar Belakang : Penyakit ginjal kronik (PGK) didefinisikan sebagai kelainan struktur atau fungsi ginjal lebih dari 3 bulan, dengan implikasi terhadap kesehatan. PGK menyebabkan gangguan regulasi metabolisme mineral dan selanjutnya terjadi perubahan dalam bone modeling, remodeling, dan pertumbuhan. Perubahan ini disebut chronic kidney diseasae – mineral and bone disorders (CKD-MBD) yaitu kondisi sistemik yang bermanifestasi pada abnormalitas hormon paratiroid (PTH), kalsium, fosfor dan vitamin D. Abnormalitas PTH akan mengakibatkan gangguan kematangan tulang pada anak PGK. Pengukuran kematangan tulang dilakukan dengan pemeriksaan foto Bone Age pada manus kiri. Tujuan : Sebagai studi awal dalam mendeskripsikan usia tulang dengan pemeriksaan bone age dan mengukur kadar PTH pada PGK stadium 3-5. Metode : Penelitian merupakan deskriptif analitik yang dilakukan prospektif dengan desain cross sectional, didapatkan 18 pasien anak yang dipemeriksaan kadar PTH dan X-Ray Bone Age pada manus kiri dalam 1 waktu. Penilaian Bone Age dilakukan oleh 2 dokter ahli subradiologi anak. Hasil : 18 pasien anak dengan PGK didapatkan 16 anak (88,89 %) hiperparatiorid dengan 11 anak (68,8 %) mengalami gangguan usia tulang (kategori terlambat). Dilakukan uji T tak berpasangan menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna rerata kadar PTH antara kelompok anak dengan usia tulang terlambat dan sesuai (p>0,05), namun rerata PTH pada kelompok usia tulang terlambat lebih besar (317,65 ± 181,17) dibanding kelompok usia tulang sesuai (288,9 ± 173,43). Kata Kunci: Bone Age, Penyakit ginjal kronik, Gangguan usia tulang, Hiperparatiorid

Nilai apparent diffusion coefficient (ADC) sebagai prediktor keganasan pada meningioma
Latar Belakang : Meningioma merupakan tumor otak tersering mencapai 20-32% dari seluruh tumor intrakranial pada orang dewasa. MRI dengan diffusion weighted imaging (DWI) dan apparent diffusion coefficient (ADC) dapat dilakukan guna evaluasi pra operasi dalam perencanaan tindakan terhadap tumor-tumor otak. DWI telah dinilai berguna untuk mengeksplorasi tumor otak primer dan nilai ADC telah terbukti bermanfaat untuk membedakan antara lesi jinak dan ganas. Tujuan : Mengetahui kemungkinan nilai ADC sebagai prediktor keganasan dari meningioma. Metode : Nilai ADC yang telah dikumpulkan di olah, sehingga didapatkan nilai Cut off Point yang selanjutnya menggunakan uji diagnostik dinilai sensitifitas dan spesifisitasnya sebagai prediktor keganasan dari meningioma. Hasil : Didapatkan nilai ADC dengan nilai diagnostik AUC > 0,5 dengan sensitivitas sekitar 60 - 66,6% dan spesifisitas 60 – 65,7%. Kesimpulan : Nilai ADC dapat digunakan sebagai prediktor keganasan dari meningioma Kata Kunci : ADC, Meningioma, Keganasan

Rasio hounsfield unit : hematokrit dan rasio hounsfield unit : hemoglobin sebagai prediktor kejadian cerebral venous sinus thrombosis : Studi menggunakan non enhaced computed tomography dan digital subtraction angiography
Latar Belakang : Cerebral venous sinus thrombosis (CVST) merupakan kelainan thromboemboli yang langka, multifactorial, memiliki gejala klinis yang luas, serta sulit untuk didiagnosis. Gold standard penegakkan diagnosa CVST adalah modalitas invasif menggunakan digital substraction angiography (DSA). Modalitas lain yang sifatnya non-invasif, cepat dan lebih murah dalam menegakkan diagnosa CVST adalah non enhance computed tomography (NECT). Temuan NECT yang dapat digunakan sebagai prediktor kejadian CVST adalah peningkatan nilai Hounsfield unit(HU) padasinus sagitalis superior (SSS),tetapi temuan ini tidak spesifik dan dapat ditemukan pada pasien non-thrombus dengan peningkatan nilai hematokrit dan hemoglobin (hemokonsentrasi). Oleh karena itu dibuat rasio antara Hounsfield unit dengan hematokrit (rasio HU:HT) dan hemoglobin (rasio HU:HB)dan dianalisis kemampuannya sebagai prediktor kejadian CVST. Tujuan : Mengetahui nilai rasio HU:HT dan rasio HU:HBsebagai prediktor kejadian CVST. Metode :Nilai rasio HU:HT dan HU:HB dari 35 pasien CVST dan 35 pasien non-CVSTdikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan cut off point, serta dinilaisensitivitas dan spesifisitas-nya. Hasil : Perbedaan signifikan didapatkan pada nilai rasio HU:HT(1.73 ± 0.12 vs 1.43 ± 0.17) dan rasio HU:HB (5.10 ± 0.53 vs 4.26 ± 0.55) pada pasien CVST dan non-CVST. Nilai cut offpoint rasio HU:HT ± 1.57 memiliki sensitivitas 100% dan spesifisitas 78% sedangkan nilai cut off point rasio HU:HB ± 4.70 memiliki sensitivitas 82% dan spesifisitas 80%. Kesimpulan : Nilai rasio HU:HT danrasio HU:HBdapat digunakan sebagai prediktor kejadian CVST Kata Kunci :cerebral venous sinus thrombosis, HU:HT ratio, HU:HB ratio

Hubungan ketebalan korteks dan volume ginjal dengan GFR pada penyakit ginjal kronik : Studi kasus di RSUP dr. Kariadi Semarang
Latar belakang: Pada penyakit ginjal kronis (PGK), keparahan penyakit didasarkan pada kerusakan ginjal, yang dihitung melalui penurunan estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) yaitu

Hubungan kadar fosfat dengan ketebalan tunika intima-media arteri carotis secara ultrasonografi pada penyakit ginjal kronik anak
Latar Belakang : Salah satu komplikasi chronic kidney disease – mineral and bone disorder (CKD-MBD) adalah kalsifikasi vaskular. Kalsifikasi tunika media terjadi akibat perubahan fungsi vascular smooth muscle cells (VSCM) ke osteoblast-like cells. Peningkatan kadar fosfat telah terbukti mempengaruhi VSCM menyebabkan terjadinya adaptasi dan kerusakan selular yang akhirnya mendorong terjadinya kalsifikasi. Pemeriksaan carotid intima media thickness (CIMT) dapat digunakan sebagai penanda tahap dini kejadian kalsifikasi vaskular pada pembuluh darah di tempat yang lain. Tujuan : Mengetahui hubungan kadar fosfat dengan CIMT. Metode : Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional. Pengumpulan data penelitian dilakukan di Departemen Radiologi RSUP dr. Kariadi Semarang. Sampel penelitian adalah kadar fosfat pada pasien PGK anak stadium 3-5 dan pemeriksaan CIMT. Kemudian dilakukan uji korelasi Rank-Spearman untuk menganalisis hubungan kadar fosfat dengan carotid intima-media thickness (CIMT). Hasil : Dua puluh delapan pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diikutssertakan dalam penelitian ini. Rerata usia pasien adalah 13,25 ± 3,46 tahun. Distribusi jenis kelamin adalah laki-laki berjumlah 18 orang (64,3 %) dan perempuan berjumlah 10 orang (35,7 %). Rerata kadar fosfat pada penelitian ini adalah 4,85 ± 1,94 mg/dl. Rerata CIMT pada keseluruhan subyek penelitian ini adalah 0,49 ± 0,09 mm. Berdasarkan uji korelasi Rank-Spearman didapatkan nilai p = 0,023 (p < 0,05) dan nilai rho =0,428. Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara kadar fosfat dengan ketebalan tunika intima-media arteri karotis pada anak PGK Kata Kunci : CIMT, VSCM, fosfat, PGK

Hubungan sacral ratio dengan letak malformasi anorectal pada pemeriksaan lopografi distal
Malformasi anorektal (MAR) merupakan kelainan kongenital tanpa anus atau dengan anus tidak sempurna. Banyak anak-anak dengan malformasi ini memiliki anomali lain diantaranya malformasi sacrum yang berhubungan dengan prognosis fungsional pada pasien paska operasi. Penelitian ini dilakukan pada pasien MAR yang telah dilakukan pemeriksaan lopografi distal post colostomi dan dinilai index sacral rationya berdasarkan letak MAR apakah berada dalam range normal atau dibawah nilai normal. Pada penelitian terdahulu didapatkan adanya korelasi antara nilai sacral ratio dengan letak MAR. Prognosis dalam fungsi kontinensia juga cenderung lebih buruk pada pasien dengan nilai sacral ratio rendah. Penulis tidak menemukan data tentang nilai sacral ratio dengan hubungannya terhadap letak MAR sehingga mengangkat kasus malformasi anorektal agar penegakan diagnosa dan pemilihan manajemen terapi dapat sedini mungkin sehingga komplikasi post operasi dapat diminimalisir. Penelitian ini dengan jumlah sampel 32 sampel dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok dengan rentang usia dibawah 1 tahun dan kelompok dengan rentang usia di atas sama dengan 1 tahun pada saat dilakukan pengukuran sacral ratio. Pasien MAR yang telah dilakukan tindakan operasi pada daerah anus dan pasien MAR dengan riwayat patah tulang maupun deformitas pada daerah pelvis serta sacrum akan di eksklusi. Pada penelitian ini didapatkan adanya korelasi antara letak MAR dengan nilai sacral ratio, dimana semakin tinggi letak MAR maka semakin rendah nilai sacral rationya. Anak dengan malformasi anorektal cenderung memiliki penilaian sacral rasio yang rendah pada defek letak tinggi serta penilaian sacral ratio yang rendah tampak berkorelasi dengan prognosis fungsional yang buruk. Kata kunci : malformasi anorectal; sacral ratio, lopografi distal

Korelasi kadar HBA1C dengan derajat stenosis arteri infrapopliteal pada pasien dengan critical limb ischemia : Studi menggunakan pemeriksaan arteriografi
Latar belakang : Critical limb ischemia (CLI) adalah sindrom klinis dari nyeri iskemik saat istirahat dan atau adanya kehilangan jaringan seperti ulkus yang tidak sembuh atau gangren yang terkait dengan peripheral artery disease (PAD) dari ekstremitas bawah. Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Di dalam darah, glukosa bereaksi dengan hemoglobin membentuk hemoglobin A1c (HbA1c), semakin banyak glukosa di dalam darah, semakin banyak HbA1c yang terbentuk di dalam darah. Peningkatan kadar HbA1c merupakan indikator positif adanya kadar glukosa darah yang tidak terkontrol (tidak terkendali). Kadar glukosa yang tinggi (hiperglikemia) merupakan faktor risiko bagi terjadinya aterosklerosis. Arteriografi masih digunakan sebagai gold standard untuk evaluasi penyakit arteri perifer, termasuk pada arteri infrapopliteal. Tujuan : Mengetahui korelasi antara kadar HbA1c dengan derajat stenosis arteri infrapopliteal pada pasien dengan Critical Limb Ischemia. Metode : Penelitian belah lintang (cross-sectional) menggunakan data sekunder rekam medis terhadap pasien Critical Limb Ischemia yang telah dilakukan pemeriksaan kadar HbA1c dan arteriografi. Dilakukan pencatatan kadar HbA1c serta derajat stenosis pada arteri peroneal, tibialis anterior dan tibialis posterior, kemudian dilakukan uji korelasi spearman. Hasil : Uji korelasi spearman kadar HbA1c terhadap derajat stenosis arteri infrapopliteal pada pasien CLI menunjukkan nilai uji signifikasi (p=0.097). Kesimpulan : Tidak terdapat korelasi yang bermakna antara kadar HbA1c terhadap derajat stenosis arteri infrapopliteal pada pasien dengan Critical Limb Ischemia. Kata kunci : Critical Limb Ischemia, Arteriografi, Stenosis arteri infrapopliteal, kadar HbA1c

Korelasi kadar serum fosfor darah dengan kejadian sarcopenia pada wanita lanjut usia : Studi menggunakan pemeriksaan dual-energy X-ray absorptiometry (DXA)
Insidensi sarcopenia cukup tinggi pada orang lanjut usia, dengan beberapa dampak negatif yang mempengaruhi kualitas hidupnya. Patogenesis sarcopenia sendiri sangat kompleks dan melibatkan beberapa faktor dalam perkembangannya. Kekurangan kadar serum fosfor dalam darah dapat menyebabkan terjadinya sarcopenia, tetapi kejadian sarcopenia bisa disebabkan faktor lainnya, seperti faktor hormonal, indeks massa tubuh yang tidak normal, dan gaya hidup. Penelitian cross-sectional ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa Posyandu Lansia di Semarang yang dimulai sejak Oktober 2018 hingga Juli 2019. Terdapat 28 responden wanita yang berusia lebih dari 60 tahun yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Responden yang mengkonsumsi suplemen fosfor secara rutin dieksklusikan dari penelitian ini. Seluruh responden secara sukarela mengikuti penelitian ini dan telah menandatangani informed consent. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar serum fosfor darah dengan kejadian sarcopenia. Status sarkopenia diperoleh dari pemeriksaan sceletal muscle index (SMI) yang diperoleh dari pemeriksaan Dual energy X-ray absorptiometry (DXA), handgrip strength, dan gait speed test. Kadar serum fosfor diperoleh dari uji laboratorium darah. Penelitian ini semakin membuktikan bahwa DXA terbukti sebagai pemeriksaan yang cukup bisa diandalkan untuk mengevaluasi massa otot. Hasil penelitian ini, diperoleh responden dengan sarcopenia tidak ada responden dari kelompok sarcopenia maupun non sarcopenia memiliki kadar serum fosfor dibawah 2,5 mg/dl. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara kadar serum fosfor dalam darah dengan kejadian sarcopenia. Kata Kunci : Sarcopenia; kadar serum fosfor; massa otot, DXA
 Karya Umum
Karya Umum 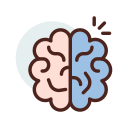 Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial 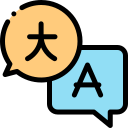 Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 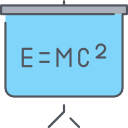 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 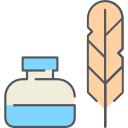 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 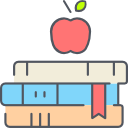 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah