Ditapis dengan

Perbandingan efektivitas chair-based exercise dan senam lansia dalam meningkatkan keseimbangan lanjut usia
Tujuan : Membandingkan (menganalisis) perbedaan efektivitas Chair based exercise (CBE) dan Senam Lansia (SL) dalam meningkatkan keseimbangan pada lanjut usia. Rancangan : Quasi Experiment. Subjek : 22 lanjut usia di Panti Werda usia 60 - 74 tahun. Tempat: Penelitian dilakukan di Panti Wredha Rindang Asih II, Panti Werda Usia Bethany dan Panti Wreda PELKRIS Semarang. Waktu : 29 Juli - 6 September 2019. Perlakuan : Kelompok CBE (n=12) diberikan chair – based exercise dengan frekuensi 5 kali seminggu selama 6 minggu. Kelompok Senam Lansia (n=10) diberikan latihan senam lansia dengan frekuensi 5 kali seminggu selama 6 minggu. Hasil Pengukuran Utama : Skor keseimbangan yang diukur dengan Berg Balance Scale (BBS). Penilaian dilakukan sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan terakhir. Hasil : Pada awal penelitian skor, BBS pre antara kelompok CBE (42,5; 35-50) dengan kelompok SL (41; 38-53) tidak didapatkan perbedaan bermakna dengan p = 0,771. Pada kelompok CBE terdapat perbedaan bermakna skor BBS post (44,5; 38-53) dibandingkan skor BBS pre 42,5; 35-50) dengan p = 0,000. Pada kelompok SL skor BBS post (45;41-56) dibandingkan dengan BBS pre (41; 38-53) terdapat perbedaan bermakna dengan p = 0,004. Terdapat perbedaan bermakna delta skor BBS (p =

Efek prehabilitation exercise terhadap performa fungsionak pasien osteoartritis yang menjalani total knee replacement
Latar belakang : Total knee replacement (TKR) merupakan pilihan terapi pada pasien Osteoarthritis manakala terapi konservatif gagal. Program latihan penguatan seperti prehabilitation exercise menggunakan resistance bands diharapkan dapat meningkatkan performa fungsional pasca TKR yang diukur dengan tes Timed Up and Go (TUG) dan skor fungsional WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis). Metode : 16 pasien yang memenuhi kriteria dibagi dalam kelompok perlakuan (n=8) dan kelompok kontrol (n=8). Kelompok perlakuan mendapatkan prehabilitation exercise menggunakan resistance bands 3 kali seminggu selama 4 minggu, sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan latihan penguatan. Nilai TUG dan skor WOMAC diukur pada 4 minggu dan 1 minggu sebelum operasi, serta 8 minggu pasca operasi. Hasil : Perbandingan antar kelompok menunjukkan perbedaan signifikan nilai TUG (p=0,003) dan skor WOMAC (p=0,002) pada 1 minggu sebelum operasi sedangkan pada 8 minggu sesudah operasi didapatkan perbedaan bermakna pada nilai TUG (p=0,009) dan untuk skor WOMAC tidak didapatkan perbedaan yang bermakna (p=0,125). Kesimpulan : Prehabilitation exercise dengan resistance bands dapat meningkatkan performa fungsional pasien yang akan menjalani TKR. Kata Kunci : Prehabilitation exercise, Timed Up and Go, WOMAC, Total Knee Replacement.

Pengaruh penambahan wrist Kinesio Taping pada latihan motorik tangan terhadap kekuatan menggenggam pada anak palsi serebral
Latar Belakang : Palsi serebral merupakan penyebab tersering disabilitas pada anak-anak. Deformitas tangan yang paling umum terjadi pada anak palsi serebral spastik adalah fleksi wrist, fleksi jari, dan ibu jari yang dapat mempengaruhi kekuatan menggenggam secara bermakna. Penambahan Kinesio Taping pada latihan motorik tangan merupakan metode baru yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan menggenggam sehingga memperbaiki fungsi tangan dan meningkatkan kemadirian ADL anak palsi serebral. Tujuan : Membuktikan perbedaan kekuatan menggenggam pada anak palsi serebral yang mendapat latihan motorik tangan dengan latihan motorik tangan yang ditambah wrist Kinesio Taping. Metode : Penelitian ini merupakan simple randomized controlled pre dan post experimental design. Sampel adalah 20 anak palsi serebral spastik yang bersekolah di YPAC Semarang dan dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Kelompok intervensi (n=10, drop out 1) mendapatkan kinesio taping dan latihan motorik tangan sebanyak 3 kali seminggu selama 4 minggu. Kelompok kontrol (n=10, drop out 1) hanya mendapatkan latihan motorik tangan saja. Kekuatan menggenggam diukur dengan vigorimeter sebelum perlakuan dan akhir minggu ke-4 intervensi. Hasil : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kekuatan menggenggam anak palsi serebral yang mendapatkan latihan motorik tangan dengan penambahan wrist Kinesio Taping dengan tarikan 30% dibandingkan dengan anak palsi serebral yang mendapatkan latihan motorik tangan saja. Simpulan : Tidak didapatkan pengaruh penambahan kinesio taping terhadap peningkatan kekuatan menggenggam anak palsi serebral tipe spastik yang mendapatkan latihan motorik tangan Kata Kunci : kinesio taping, palsi serebral, kekuatan menggenggam

Perbandingan pengaruh latihan Deep Cervical Flexor dengan dan tanpa Pressure Biofeedback Unit terhadap intensitas nyeri dan forward head posture (Studi pada kru Helikopter dengan nyeri leher mekanik)
Latar Belakang : Nyeri leher mekanik adalah nyeri leher akibat disfungsi biomekanik di leher atau punggung atas, atau bersumber ke sendi, otot, ligamen, diskus, atau jaringan lunak lainnya di leher atau punggung atas. Prevalensi nyeri leher mekanik pada pilot dan kru helikopter diakui sebagai masalah medis yang signifikan di kru angkatan darat modern dengan jangka waktu 3 hingga 12 bulan dilaporkan dalam kisaran 56,6% - 84,5%. Otot leher fleksor intrinsik disebut sebagai deep cervical fleksor (DCF) dalam kondisi lemah akan menyebabkan nyeri leher dan forward head posture (FHP). Penggunaan Pressure Biofeedback Unit (PBU) berfungsi untuk meningkatkan pembelajaran motorik otot-otot yang terkena dampak melalui umpan balik visual sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot leher dalam memperbaiki postur kepala dan leher serta mengurangi nyeri. Tujuan : Membuktikan rerata penurunan intensitas nyeri dan perubahan FHP pada kru helikopter dengan nyeri leher mekanik yang mendapatkan latihan DCF dan PBU lebih besar dibandingkan dengan yang mendapat latihan DCF konvensional. Metode : Penelitian ini merupakan eksperimental randomized pre and post test group design. Sampel adalah 26 kru helikopter skadron-31/serbu dibagi menjadi 2 kelompok secara acak. Kelompok perlakuan (n=12, 1 dropout) mendapatkan latihan otot DCF dengan pressure biofeedback sebanyak 12 kali selama 4 minggu dengan frekuensi 3 kali setiap minggu. Kelompok kontrol (n=12, 1 dropout) melakukan neck exercise saja. Penilaian intensitas nyeri dengan Visual Analogue Scale ( VAS ) dan perubahan FHP dengan goniometer. Hasil : Terdapat rerata penurunan intensitas nyeri dan perubahan FHP pada kelompok perlakuan yang signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Simpulan : Rerata penurunan intensitas nyeri dan perubahan FHP pada kru helikopter dengan nyeri leher mekanik yang mendapatkan latihan DCF dan PBU lebih besar dibandingkan dengan yang mendapat latihan DCF konvensional. Kata Kunci : pressure biofeedback, nyeri leher mekanik

Efek prehabilitation exercise terhadap kekuatan otot kuadrisep femoris pada pasien osteoartritis yang menjalani total knee replacement
Latar belakang:Total Knee Replacement (TKR) merupakan pilihan terapi pada pasien Osteoarthritis lutut ketika terapi konservatif gagal. Program latihan penguatan seperti prehabilitation exercise menggunakan resistance bands diharapkan dapat meningkatkan kekuatan otot kuadrisep femoris pada pasien yang menjalani TKR. Metode: 16 subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dibagi secara acak menjadi kelompok perlakuan (n=8) dan kelompok kontrol (n=8). Kelompok perlakuan mendapatkan prehabilitation exercise 3x seminggu selama 4 minggu, sedangkan kelompok kontrol mendapatkan terapi konvensional 2x seminggu selama 4 minggu. Pengukuran kekuatan otot kuadrisep femoris dilakukan pada 4 minggu dan 1 minggu sebelum TKR, serta 8 minggu setelah TKR menggunakan push-pull dinamometer. Hasil: Perbandingan antar kelompok menunjukkan perbedaan signifikan nilai kekuatan otot kuadrisep femoris (p=0,001) pada 1 minggu sebelum TKR dan pada 8 minggu setelah TKR juga didapatkan perbedaan signifikan pada nilai kekuatan otot kuadrisep femoris (p

Pengaruh pemberian ajuvan asam folat terhadap fungsi personal dan sosial pasien skizofrenia kronik
Latar Belakang: Hasil pengobatan skizofenia menunjukkan sebanyak 85% mengalami penurunan fungsi. Remisi klinis tidak selalu mengarah pada pemulihan fungsi. Defisiensi folat diidentifikasi sebagai salah satu faktor risiko skizofrenia. Tujuan: Mengetahui manfaat ajuvan asam folat dalam memperbaiki fungsi personal dan sosial pasien skizofrenia kronis. Metode: Penelitian eksperimental dengan desain double blind - randomized controlled trial, pre post test design. Sampel penelitian dipilih secara non – probability, consecutive sampling. Subjek dibagi dalam 2 kelompok, kelompok perlakuan dan kontrol. Perlakuan dengan ajuvan asam folat 2 mg / hari selama 4 minggu. Anti psikotik yang digunakan tidak sama. PSP diukur sebelum dan sesudah perlakuan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner sosiodemografi dan kuesioner wawancara terstruktur Personal and Social Performance Scale versi Indonesia. Hasil: Terdapat 66 subjek yang memenuhi kriteria inklusi, 2 diantaranya Drop Out karena kejang dan SNM. Uji komparatif karakteristik demografik kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tidak ada perbedaan bermakna. Terdapat peningkatan skor PSP yang bermakna secara statistik p

Hubungan kejadian depresi dengan risiko bunuh diri pada usia produktif di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
Latar Belakang : Sejak tahun 2015-2019 terdapat 141 orang meninggal dunia akibat bunuh diri di Kabupaten Grobogan, dan kecamatan Purwodadi menduduki peringkat ketiga terbanyak setelah Kecamatan Gabus dan Kecamatan Wirosari dimana sebagian besar pelaku bunuh diri adalah kelompok usia produktif. Kejadian depresi sering dikaitkan sebagai faktor risiko kejadian bunuh diri. Depresi merupakan salah satu gangguan mood. Depresi dikarakteristikkan dengan kesedihan, hilangnya minat atau kegembiraan, perasaan bersalah atau tidak berguna, gangguan tidur atau nafsu makan, perasaan lelah, dan konsentrasi buruk. Dalam bentuk parahnya, depresi dapat mengarah pada keinginan bunuh diri. Tujuan : Mengetahui hubungan kejadian depresi dengan risiko bunuh diri pada usia produktif di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan belah lintang. Sampel pada penelitian ini adalah warga Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang tergabung di Posbindu dengan menggunakan metode consecutive random sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner sosiodemografi, kuesioner BDI-II dan CSSRS. Hasil : Responden usia produktif dalam penelitian ini sebagian besar (68,6%) tidak mengalami depresi. Terdapat adanya hubungan yang bermakna antara kejadian depresi dengan risiko bunuh diri pada usia produktif di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan nilai (p=0,002). Simpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara kejadian depresi dengan risiko bunuh diri. Kata Kunci : Depresi, Bunuh Diri, Purwodadi

Hubungan antara skor sequential organ failure assessment (SOFA) dengan fungsi sistolik ventrikel kanan dan tekanan pengisian ventrikel kiri pada pasien sepsis
Latar belakang: Sepsis merupakan disfungsi organ akibat disregulasi respon tubuh terhadap infeksi yang dapat dinilai dengan skor Sequential Organ Failure Assessment (SOFA). Disfungsi miokard terjadi pada 50-64% pasien sepsis. Ventrikel kanan (Right ventricle/RV) dan tekanan pengisian ventrikel kiri (Left Ventricle Filling Pressure/LVFP) berperan penting dalam regulasi hemodinamik. Tingkat keparahan sepsis berdasarkan skor SOFA yang dihubungkan dengan hasil ekokardiografi fungsi sistolik RV dan LVFP hingga kini masih belum dilaporkan. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui hubungan keparahan sepsis yang dinilai menggunakan skor SOFA dengan fungsi sistolik RV dan LVFP. Metode: Penelitian observasional desain belah lintang melibatkan 25 pasien sepsis yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi. Skor SOFA sebagai subjek penelitian dihitung sampai maksimal 3 kali per pasien paralel dengan pemeriksaan fungsi RV menggunakan ekokardiografi TAPSE, RVFAC, RVFWS, RV-PA coupling, dan LVFP menggunakan formula Nagueh dan kriteria ASE/EACVI 2016. Uji korelasi dilakukan antara skor SOFA dengan TAPSE, RVFAC, RVFWS, RV-PA coupling, dan LVFP. Hasil: Didapatkan 56 sampel skor SOFA dan ekokardiografi. Didapatkan korelasi yang bermakna antara skor SOFA dengan TAPSE (r=-0.44, p=0.001), RV FAC (r=-0.54, p=

Pengaruh aspirasi trombus selektif terhadap luaran klinis pada penderita sindroma koroner akut dengan elevasi segmen ST yang dilakukan intervensi koroner perkutan primer
Latar belakang: Embolisasi distal koroner berkontribusi terhadap tingginya kejadian kardiovaskular mayor (KKVM) pasca intervensi koroner perkutan primer (IKPP). Aspirasi trombus (AT) manual berpotensi mengurangi embolisasi distal dan memperbaiki perfusi mikrovaskular pada pasien sindroma koroner akut dengan elevasi segmen ST (SKA-EST), terutama pasien dengan badai trombus tinggi. Tujuan: Mengetahui pengaruh aspirasi trombus selektif terhadap luaran klinis pasca IKPP. Metode: Penelitian kohort retrospektif pada pasien SKA-EST dengan onset ≤12 jam dan TIMI Trombus awal grade ≥3 yang menjalani IKPP dengan aspirasi trombus selektif di RSUP Dr. Kariadi periode Januari 2016 – Desember 2019. Luaran klinis yang diobservasi adalah KKVM selama rawat inap yang terdiri dari mortalitas, syok kardiogenik, edema paru akut, aritmia, revaskularisasi ulang, dan stroke. Hasil: Sejumlah 196 pasien memenuhi kriteria, terdiri dari 96 pasien kelompok AT dan 100 pasien kelompok Non-AT. Angka keberhasilan angiografi pada kelompok AT sebesar 97,9%. Kelompok AT mengalami penurunan TIMI trombus lebih baik dibanding kelompok Non-AT (4,31 vs 4,11, p=0,012). Terdapat 15 pasien kelompok AT (15,6%) dan 20 pasien kelompok Non-AT (20%) yang mengalami KKVM pasca IKPP (RR 1,055, IK 95% 0,926-1,202, p=0,424). Pada pasien dengan TIMI Trombus awal grade 5, KKVM pada kelompok AT terjadi lebih sedikit dibanding kelompok Non-AT (13,2% vs 42,9%, p=0,01). Kesimpulan: Aspirasi trombus selektif tidak berpengaruh terhadap KKVM selama rawat inap pasca IKPP. Bila aspirasi trombus dilakukan pada pasien dengan TIMI Trombus awal grade 5, berpotensi menurunkan KKVM pasca IKPP. Kata kunci: Aspirasi trombus selektif, intervensi koroner perkutan primer, kejadian kardiovaskular mayor, sindroma koroner akut dengan elevasi segmen ST, embolisasi distal.

Korelasi antara rasio CD4+/CD8+ dengan nilai flow mediated dilatation arteri brachialis dan ankle brachial index pada pasien HIV
Latar Belakang : Pasien dengan human immunodeficiency virus (HIV) berrisiko mengalami peripheral arterial disease (PAD), dan rasio CD4+/CD8+ berhubungan dengan aterosklerosis. Nilai flow mediated dilatation (FMD) arteri brachialis dan ankle brachial index (ABI) merupakan pendanda yang sensitif untuk menilai disfungsi endotel dan PAD. Hingga saat ini, belum ada penelitian mengenai korelasi antara rasio CD4+/CD8+ dengan nilai FMD dan ABI pada pasien HIV. Metode : Penelitian analitik observasional dengan desain belah lintang pada pasien HIV. Nilai FMD arteri brachialis diperiksa menggunakan ultrasonografi B-mode, ABI dengan membandingkan tekanan darah sistolik kedua lengan dan kaki. Jumlah CD4+ nadir diperoleh dari rekam medis, sedangkan CD4+ aktual, CD8+ aktual, CD4+%, CD8+% dan rasio CD4+/CD8+ diperiksa dengan flow cytometry. Korelasi antara rasio CD4+/CD8+ dengan FMD dan ABI dianalisis dengan Pearson/ Spearman correlation. Hasil : Didapatkan 57 pasien HIV, dengan usia 31 (19-50) tahun dan rata-rata lama terdiagnosis HIV serta durasi konsumsi ARV 24 bulan, dimana 41 (71,9%) subjek mengalami penurunan nilai FMD, dan 9 (15,8%) subjek dengan ABI di bawah normal (≤0,90). Median nilai FMD adalah 5,8% dan rerata ABI adalah 0,98±0,07. CD4+% dan rasio CD4+/CD8+ berkorelasi positif dengan nilai FMD (r=0,27; p=0,04 dan rs=0,31; p=0,02). CD8+ aktual dan CD8+% berkorelasi negatif dengan nilai FMD (rs=-0,29; p=0,03 dan r=-0,32; p=0,02). Baik CD4+, CD8+ maupun rasio CD4+/CD8+ tidak berkorelasi dengan ABI. Simpulan : Pasien HIV mengalami disfungsi endotel yang ditandai dengan penurunan nilai FMD arteri brachialis. Rasio CD4+/CD8+ sebagai penanda aktivitas inflamasi kronik berkorelasi positif lemah dengan nilai FMD arteri brachialis, tetapi tidak dengan ABI. Kata Kunci : rasio CD4+/CD8+, disfungsi endotel, PAD, HIV
 Karya Umum
Karya Umum 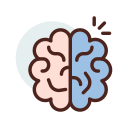 Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial 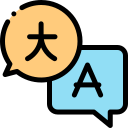 Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 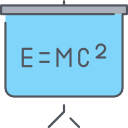 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 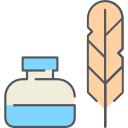 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 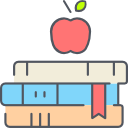 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah