Ditapis dengan

Pengaruh remote ischemic preconditioning terhadap kejadian kardiovaskular mayor selama rawat inap pasca intervensi koroner perkutan primer : Uji klinis pada pasien infark miokard akut dengan elevasi segmen ST dengan keterlambatan reperfusi di RSUP dr. Kariadi Semarang
Latar belakang: Keterlambatan reperfusi pada infark miokard akut dengan elevasi segmen ST (IMA-EST) berkontribusi terhadap tingginya kejadian kardiovaskular mayor selama rawat inap pasca intervensi koroner perkutan primer (IKPP). Remote ischemic preconditioning (RIPC) dapat memberikan kardioproteksi tambahan dan menurunkan luas infark miokard, sehingga diharapkan mampu memperbaiki luaran klinis pasca IKPP pada pasien IMA-EST dengan keterlambatan reperfusi yang signifikan. Tujuan: Mengetahui pengaruh RIPC terhadap kejadian kardiovaskular mayor selama rawat inap pasca IKPP pada pasien IMA-EST dengan keterlambatan reperfusi yang signifikan. Metode: Pasien IMA-EST yang menjalani IKPP dengan onset ≤ 12 jam atau > 12 jam disertai nyeri dada yang terus berlangsung dan mengalami keterlambatan reperfusi (waktu door to wire crossing > 90 menit dan waktu total iskemik > 180 menit) dirandomisasi ke dalam kelompok RIPC (IKPP standar ditambah prosedur RIPC) atau kontrol (IKPP standar). Kejadian kardiovaskular mayor selama rawat inap merupakan kombinasi kejadian mortalitas, stroke, aritmia, edema paru akut atau syok kardiogenik. Hasil: Dalam analisis terhadap 35 pasien kelompok RIPC dan 35 pasien kelompok kontrol, tidak terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok dalam komponen-komponen kejadian kardiovaskular mayor: mortalitas (p = 0,356), aritmia (p= 0,114), edema paru akut (p = 0,356) dan syok kardiogenik (p= 1,00), namun kombinasi komponen kejadian kardiovaskular mayor secara bermakna lebih rendah pada kelompok RIPC (5,7%) dibandingkan dengan kelompok kontrol (25,7%), (RR = 0,222, 95% CI 0,052 – 0,956, p = 0,022). ΔCK-MB kelompok RIPC = 292 (200 – 426) U/L lebih rendah daripada ΔCK-MB kelompok kontrol = 437 (373 – 567) U/L, (p=0,024). Kesimpulan: RIPC secara statistik menurunkan kejadian kardiovaskular mayor selama rawat inap pasca IKPP pada pasien IMA-EST dengan keterlambatan reperfusi yang signifikan. Kata kunci: remote ischemic preconditioning, intervensi koroner perkutan primer, kejadian kardiovaskular mayor, infark miokard akut dengan elevasi segmen ST, keterlambatan reperfusi.

Perubahan nilai global longitudinal strain ventrikel kiri pada penderita karsinoma payudara paska pemberian kombinasi cyclophosphamide, adriamycin dan 5-fluorouracil
Latar belakang : Kemoterapi dapat menyelamatkan banyak penyintas kanker payudara. Namun efek samping kemoterapi Cyclophosphamide, Adriamycin dan 5-Fluorouracil (CAF) diduga menyebabkan penurunan Global Longitudinal Strain (GLS). Tujuan : Melihat apakah terdapat penurunan GLS pada pasien karsinoma payudara yang diberikan kemoterapi CAF pada Siklus 1,2 dan 3 dibandingkan sebelum diberikan kemoterapi. Metode : Studi Prospektif Observasional Analitik dari pasien rawat jalan dengan diagnosis karsinoma payudara, yang tidak terdapat disfungsi ventrikel dan diberikan kemoterapi CAF. Setiap pasien dilakukan pemeriksaan GLS setiap siklus. Hasil : Terdapat 37 subyek dengan rerata usia 52,76+11,39 tahun. Terdapat penurunan GLS disetiap siklus kemoterapi dibandingkan baseline yang signifikan secara statistik (p

Korelasi antara nilai right ventricular strain dengan kadar asam urat pada pasien hipertensi arteri paru
Latar Belakang: Hipertensi arteri paru dapat menyebabkan kegagalan ventrikel kanan akibat hipertrofi dan dilatasi pada ventrikel kanan. Penelitian sebelumnya menyebutkan iskemia miokardium yang terjadi pada hipertrofi ventrikel kanan dapat mengakibatkan peningkatan kadar asam urat. Korelasi antara fungsi ventrikel kanan dan kadar asam urat belum banyak diteliti. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menilai korelasi antara fungsi ventrikel kanan yang dinilai menggunakan right ventricular strain dengan kadar asam urat pada pasien hipertensi arteri paru. Metode: Penelitian ini adalah penelitian belah lintang pada pasien hipertensi arteri paru yang terkonfirmasi dengan kateterisasi jantung kanan. Didapatkan 25 pasien yang dilakukan penilaian right ventricular strain dengan ekokardiografi dan kadar asam urat. Hasil: Dari 25 subjek didapatkan rerata usia adalah 34,12±11,9 tahun dengan mayoritas perempuan. Rerata indeks massa tubuh pada sampel penelitian yaitu sebesar 19,69±2,6 kg/m2. Rerata diameter basal ventrikel kanan yaitu sebesar 4,15±1,2 cm, rarata luas area atrium kanan yaitu sebesar 22,842±10,7 cm2. Etiologi hipertensi paru tebanyak adalah defek septum atrium (60%). Rerata right ventricular strain sebesar 18,41±4,0, rerata kadar asam urat yaitu sebesar 5,57±1,0 mg/dl. Semua subjek mendapatkan obat monoterapi vasodilator pembuluh darah paru, tidak mendapatkan diuretik dan obat penghambat xanthine oxidase. Didapatkan korelasi negatif antara nilai right ventricular strain dengan kadar asam urat (p = 0,024 ; r = - 0,449). Kesimpulan : Terdapat korelasi antara nilai right ventricular strain dengan kadar asam urat pada pasien hipertensi arteri paru. Kata Kunci: right ventricular strain, asam urat, hipertensi arteri paru.

Perbedaan kadar procollagen of type-1 carboxy-terminal propeptide antara atlet latih ketahanan dan non-atlet
Latar Belakang: Latihan fisik yang dilakukan atlet latih ketahanan dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi, serta periode waktu yang lama dapat meningkatkan risiko morbiditas kardiovaskular yaitu artimia, penyakit jantung koroner dan fibrosis mikardium. Procollagen of Type-I carboxy terminal propeptide (PICP) merupakan suatu biomarker penanda sintesis kolagen-I yang akan meningkat pada kondisi profibrosis. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk membedakan antara kadar PICP sebagai penanda sintesis kolagen-I pada atlet latih ketahanan dan non-atlet. Metode: Penenelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancang bedah lintang pada 18 atlet latih lari jarak jauh dan 18 non-atlet. Kadar serum PICP diperiksa dengan metode ELISA. Hasil: Dari 18 atlet dan 18 non-atlet didapatkan rerata usia (22,1±2,76) dan (22±1,18) dengan seluruhnya laki-laki. Pada kelompok atlet telah menjalani periode latihan rerata selama 6 tahun (5-8 tahun) dan jarak lari/minggu 25km (25- 50km). Pada pemeriksaan kadar serum PICP didapatkan kadar PICP serum pada atlet lebih tinggi (3944,72±211,43) dibandingkan dengan non-atlet (1761,22±369,86) P

Validasi eksternal prediktor kejadian kardiovaskular mayor selama rawat inap pada penderita infark miokard akut dengan elevasi segmen ST yang menjalani intervensi koroner perkutan primer : Studi kasus di RSUP dr. Kariadi Semarang
Latar Belakang: Skor risiko KARIADI merupakan sistem skor dengan rentang skor 0-9; komponennya meliputi kelas Killip, final TIMI flow, total ischemic time, kadar kreatinin darah, kadar glukosa darah, tekanan darah sistolik, dan usia. Skor tersebut dikembangkan untuk memprediksi risiko kejadian kardiovaskular mayor (KKvM) selama rawat inap (gabungan kematian, stroke, urgent revascularization, syok kardiogenik, edema paru akut, atau aritmia) pada penderita infark miokard akut dengan elevasi segmen ST (IMA-EST) yang menjalani intervensi koroner perkutan (IKP) primer, namun performa skor risiko tersebut belum pernah divalidasi secara eksternal. Tujuan: Melakukan validasi eksternal terhadap skor risiko KARIADI. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kohort prospektif pada 109 penderita IMA-EST yang menjalani IKP primer di RSUP Dr. Kariadi dari Januari-November 2020. Sampel penelitian menjalani penilaian skor risiko KARIADI dan follow-up selama rawat inap untuk menentukan ada/tidaknya KKvM. Validasi dilakukan dengan menguji performa kalibrasi [dinilai dengan calibration-in-the-large (alfa), calibration slope (beta), serta plot kalibrasi] dan diskriminasi (dinilai dengan c-statistic dan kurva receiver operating characteristic). Hasil: Delapan belas pasien (16,5%) mengalami KKvM. Skor risiko KARIADI menunjukkan performa kalibrasi yang kurang baik (alfa -0,39; beta 0,71; plot kalibrasi kurang sesuai) dan performa diskriminasi sedang (c-statistic 0,75; IK95% 0,62-0,87). Kesimpulan: Skor risiko KARIADI belum valid dalam memprediksi KKvM selama rawat inap pada penderita IMA-EST yang menjalani IKP primer. Kata Kunci: Infark miokard akut dengan elevasi segmen ST, intervensi koroner perkutan primer, kejadian kardiovaskular mayor, skor risiko KARIADI, validasi eksternal

Buku pedoman penggunaan jamu yang tepat bagi lansia
Obat tradisional seperti jamu biasanya digunakan untuk mengobati nyeri dan keluhan kesehatan lainnya. Pada lansia dalam upaya pengobatan merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan jamu. Sebagianbesar lansia tidak melakukan konsultasi/pemberitahuan penggunaan obat tradisional tersebut kepada petugas kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan medication error. Medication error merupakan masalah utama dalam sistem kesehatan, dapat mengurangi efektivitas terapi dan menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan. Medication error yang dimaksud adalanyakah kejadian polifarmasi atau penggunaan obat dalam jumlah banyak atau melebihi yang dibutuhkan untuk kepentingan medis. Materi yang dibahas dalam buku ini adalah: Bab 1, Pendahuluan Bab 2. Prinsip Pemanfaatan an Penggunaan Jamu Bab 3. Prinsip Pemanfaatan Jamu Bab 4. Jenis Jamu Dan Manfaatnya Bab 5. Penutup

Pengaruh pemberian antibiotik dengan kadar prokalsitionin pada anak sepsis
Latar belakang: Sepsis merupakan penyebab utama kematian pada anak seluruh dunia. Sepuluh persen diantaranya berprogres menjadi berat sehingga membutuhkan tatalaksana yang cepat dan agresif. Di ICU RSCM, 19,3% dari 502 pasien anak dirawat mengalami sepsis dengan angka kematian 54%. Prokalsitonin menjadi salah satu biomarker yang sensitif terhadap sepsis. Pemberian antibiotik untuk infeksi, adanya perbaikan akan ditunjukkan dengan penurunan kadar Prokalsitonin dengan mempertimbangkan derajat sepsis akan mengurangi lamanya pemberian antibiotik, dan mengurangi terjadinya resistensi obat. Tujuan: membandingkan perbedaan lama pemberian antibiotik terhadap kadar prokalsitonin pada anak dengan sepsis. Metode: Penelitian ini merupakan analytic observational study dilakukan di PICU dan HCU RSUP Dr. Kariadi. Subyek sejumlah 31 anak merupakan pasien anak dengan sepsis yang dirawat dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dan kemudian dianalisis dengan uji Mann Whitney dan Wilcoxon. Hasil: Sejumlah 31 anak dengan sepsis diikutkan dalam penelitian. Rerata kadar prokalsitonin sebelum mendapat antibiotik dan 5 hari setelah mendapat antibiotik didapatkan kadar Prokalsitonin menurun pada hari kelima dengan delta 0,86 ng/mL. Perubahan kadar prokalsitonin setelah pemberian antibiotik 5 hari dibanding pemberian antibiotik 1 hari signifikan (p

Perbandingan pemberian analgetik pasca operasi bupivacaine isobarik 0.125% kontinu syring pump dengan bupivacaine isobarik 0.125% bolus dilihat dari kadar neutrofil pada pembedahan orthopedi ekstremitas bawah
Latar belakang : Pembedahan orthopedi ekstremitas bawah merupakan tindakan pada bagian bawah yang meliputi tulang, sendi dan vaskuler. Pembedahan dapat menimbulkan suatu respon stress dalam bentuk metabolik dan fisiologis, sehingga mengubah berbagai respon inflamasi. Inflamasi (peradangan) merupakan reaksi kompleks pada jaringan ikat yang memiliki vaskularisasi akibat stimulus eksogen maupun endogen. Neutrofil memainkan peran utama dalam respon inflamasi dan pertahanan terhadap infeksi pada tubuh. Bupivakain juga ditemukan dapat menekan nyeri karena inflamasi dengan cara menghambat jalur sinyal NF-Kb, mikroglia spinal, dan astrosit. Bupivakain memiliki aktivitas anti inflamasi sistemik yang berperan dalam efek anti alodinia. Penelitian dilakukan karena adanya penelitian terdahulu yang masih bertentangan. Tujuan : Mengetahui perbandingan antara pemberian analgetik pasca operasi bupivakain isobarik 0.125% kontinu syring pump dibandingkan pemberian bupivakain 0.125% bolus dalam menekan reaksi inflamasi pada pembedahan ortopedi ekstremitas bawah. Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik eksperimental dengan desain pre dan post test. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok bolus dan pemberian secara kontinu setelah dilakukan tindakan dilakukan pencatatan sebagai hasil follow up setiap subjek penelitian. Pada penelitian ini terdapat 36 sampel penelitian yang terdiri dari 18 pasien (50%) sebagai kelompok dengan pemberian bupivakain isobarik 0.125% syring pump jalan 4 cc/jam dan 18 pasien (50%) sebagai kelompok dengan pemberian bupivakain isobarik 0.125% bolus 10 cc/6 jam. Kedua kelompok diberikan analgetik multimodal ketorolac 30 mg/8 jam post operasi. Hasil : Perbandingan pemberian analgetik pasca operasi bupivacaine isobarik 0.125% kontinu syring pump dengan bupivacaine isobarik 0.125% bolus dilihat dari kadar netrofil pada pembedahan orthopedi ekstremitas bawah secara statistik tidak berbeda bermakna. Secara umum perbandingan kedua kelompok data distribusi rerata BB, TB, BMI, sistolik, diastolik, dan HR didapatkan nilai p > 0.05. Kesimpulan : Penggunaan analgetik pascaoperasi bupivacaine 0,125% secara kontinu syring pump maupun secara bolus menunjukan hasil yang sama baiknya dalam menekan reaksi inflamasi pada pembedahan orthopedi ekstremitas bawah. Kata Kunci : anestesi; analgetik; epidural; neuraksial; NRS

Perbedaan teknik hiperventilasi antara peningkatan volume tidal dan laju nafas terhadap end tidal CO2 pada laparoskopi posisi trendelenburg
Latar Belakang: Pembedahan laparoskopi menggunakan CO2 ternyata membawa resiko yang dapat menyebabkan komplikasi emboli gas. 69% kejadian terjadi pada laparoskopi kolesistektomi, 17,1% pada Endoscopic Vein Harvesting. Prosedur laparoskopi ginekologis dilakukan dalam posisi trendelenburg. Posisi trendelenburg dapat mempengaruhi sistem respirasi. Insuflasi CO2 yang masif selama laparoskopi bisa dideteksi dengan ETCO2. CO2 dipengaruhi peningkatan tekanan intra abdominal kemudian menyebabkan hiperkapnia. Tujuan: Mengetahui efek perbedaan teknik hiperventilasi dengan peningkatan volume tidal dibandingkan dengan peningkatan laju nafas terhadap ETCO2 selama operasi laparoskopi posisi trendelenburg. Metode: Uji klinis acak terkontrol melibatkan 34 subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dibagi dua kelompok perlakuan, hiperventilasi dengan peningkatan volume tidal 8ml/kgBB (VT) atau peningkatan laju nafas 16x/menit (RR). ETCO2 diukur setelah intubasi, 5 menit setelah insuflasi CO2, 10 menit setelah posisi trendelenburg, diukur lagi dimenit ke 10, ke 20, ke 30 setelah perlakuan. Hasil rerata kedua kelompok dibandingkan dan dianalisis statistik. Hasil: Pada kelompok VT, rerata ETCO2 awal 41,08 ± 1,55, berbeda bermakna dengan ETCO2 akhir 31,80 ± 1,30 (p

Perbedaan pengaruh sevofluran dan propofol terhadap sistem imun dinilai dari kadar interleukin-6 dan jumlah neutrofil pada operasi bedah saraf
Latar Belakang : Imunitas bawaan adalah lini pertahanan pertama dan mengacu pada mekanisme perlindungan yang ada bahkan sebelum adanya luka / infeksi. Komponen yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan imunitas antara lain sitokin (interleukin-6) dan neutrofil. Anestesi umum dapat diberikan dengan menggunakan anestesi inhalasi, obat intravena, atau sebagian besar sering kombinasi keduanya. Semua bentuk obat anestesi ini dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan memberikan efek pada imunitas bawaan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh sevofluran dan propofol terhadap sistem imun dinilai dari kadar interleukin-6 dan neutrofil pada operasi bedah saraf. Metode : Dilakukan penelitian eksperimental terhadap 34 pasien yang menjalani operasi kraniotomi yang memenuhi kriteria penelitian. Penderita yang memenuhi kriteria penelitian dibagi kedalam dua kelompok. Kelompok I menggunakan sevofluran 1 MAC dan kelompok II menggunakan Propofol maintenance infusion 100 mcg/kg/menit.Dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan kadar interleukin-6 dan neutrofil saat sebelum operasi dan 2 jam setelah incisi. Data dianalisa secara statistik menggunakan Wilcoxon dan Mann-Whitney test, dianggap bermakna bila p < 0,05. Hasil : Pada penelitian ini didapatkan penurunan kadar neutrofil pada kelompok sevofluran sebesar 0,02 ± 7,54 % dibanding kadar awal (berbeda tidak bermakna p= 0,205) sedangkan pada kelompok propofol didapatkan peningkatan kadar neutrofil sebesar 5,07 ± 7,01% dibanding kadar awal (berbeda bermakna p=0,002). Pada perbandingan selisih kedua kelompok didapatkan perbedaan kadar neutrofil yang bermakna (p=0,003). Kadar IL-6 pada kelompok sevofluran didapatkan peningkatan sebesar 4,86 ± 6,87 pg/ml dibanding kadar awal (berbeda bermakna p=0,017) dan pada kelompok propofol juga didapatkan peningkatan sebesar 15,87 ± 16,12 pg/ml dibanding kadar awal (berbeda bermakna p=
 Karya Umum
Karya Umum 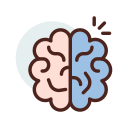 Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial 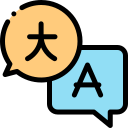 Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 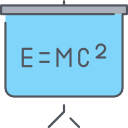 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 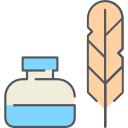 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 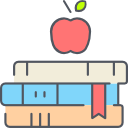 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah